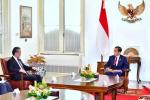Berharap Reformasi Politik di Pilkada Jakarta

SATUHARAPAN.COM - Pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Januari tahun depan di selenggarakan di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Dari data yang disajikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Setidaknya ada 215 pasang calon kepala daerah yang akan bersaing, termasuk 63 petahana.
Di antara 101 daerah yang akan memilih pemimpin, pemilihan di Jakarta memperoleh sorotan yang jauh lebih luas ketimbang daerah lain. Hal ini bisa saja terjadi, karena dinamika politik di Jakarta sebagai barometer politik di seluruh Indonesia.
Kalau dicermati, pemilihan kepala daerah 2017 tidak sebanyak tahun 2016 yang mencapai 269 daerah. Namun masih ada kemiripan, misalnya pasangan calon perorangan sekitar 22 persen (47 pasang), tidak jauh beda dengan tahun 2016 sebanyak 21 persen (155 dari total 793 pasang calon).
Sorotan pada Pilkada di Jakarta menarik karena ada hal yan baru yang diharapkan menjadi awal budaya politik yang lebih baik, yang antara lain terlihat tidak adanya calon dari kader partai politik. Meskipun belum ada data yang riil, kecenderungan ini juga terjadi di beberapa daerah.
Hal ini bisa diartikan bahwa Parpol tengah dalam krisis kaderisasi, tetapi juga bisa bermakna Parpol semakin membuka pintu bagi setiap warga negara yang mempunyai kapasitas kepemimpinan untuk didukung dalam pilkada.
Jual Beli Dukungan
Kritik dan kerisauan terbesar dalam pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005 adalah adanya praktik jual beli dukungan partai bagi calon. Nilainya terus meningkat dalam angka miliaran rupiah, dan menjadikan pilkada sebagai proses politik yang mahal. Konon ada yang menyebut pilkada di Indonesia yang tergolong termahal di dunia.
Ini kekecewaan mendasar pada Pilkada langsung. Padahal gagasan Pilkada langsung menggantikan pemilihan oleh DPRD adalah untuk mencegah maraknya praktik politik uang yang disebut sebagai politik dagang sapi. Anggota dewan dan pimpinan partai terlibat ‘’transaksi’’ untuk memilih siapa yang akan jadi kepala daerah. Alhasil, dua model itu sama mahalnya, dan sama-sama menyuburkan praktik politik uang.
Dari pengalaman pilkada langsung maupun perwakilan oleh anggota DPRD, hasilnya adalah kepala daerah yang lebih sibuk mengembalikan dana yang keluar dalam pemilihan, dan banyak yang jatuh dalam kejahatan luar biasa: korupsi. Korbannya adalah rakyat, karena pelayanan publik dan pembangunan sering dikorbankan.
Munculnya tiga pasang calon Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saifut Hidayat, Anies Baswedan – Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhooyono –Silviana Murni) diharapkan memberi angin segar dari kesesakan politik yang beracun selama ini. Ketiga pasang bukan berasal dari kader partai politik pengusung.
Prosesnya, kali ini partai opolitik yang ‘’melamar’’ calon, bukan calon yang ‘’membeli’’ dukungan partai seperti lazim pada pilkada lalu. Memang ada beberapa figur yang menawarkan untuk mendapat dukungan partai, tapi tampaknya tidak cukup laku.
Dengan perubahan ini diharapkan tidak terjadi transaksi politik dagang sapi antara calon dan partai pengusung. Sebab, dukungan partai terutama dilakukan dengan kalkulasi popularitas calon, bukan berapa uang disetor ke partai. Hal ini memberi harapan agar, setidaknya, Pilkada tidak menjadi mahal, dan menjerumuskan calon terpilih dalam kejahatan korupsi.
Popularitas vs Politik Uang
Pilkada langsung selama ini telah ‘’dirampok’’ oleh partai politik, karena keberhasilan calon diklaim sebagai kinerja partai. Dan ketika menjabat, kepala daerah terus dikejar untuk ‘’membalas budi’’ kepada politisi atau partai. Hal ini memberi beban ganda bagi calon, setelah mengeluarkan dana besar selama pemilihan. Dan hal ini menjadi mereka sangat mudah jatuh pada tindakan kejahatan korupsi.
Keterpilihan calon kepala daerah, selama ini sebenarnya didominasi oleh tingkat popularitas calon dan kinerja tim kampanye yang berada di ‘’balik layar’’, bukan oleh mesin partai politik. Hal ini makin nyata ketika muncul relawan di luar parpol yang menjadi motor utama calon yang kemudian terpilih. Hadirnya relawan ini menjadikan klepala daerah tidak bisa tidak untuk peduli dengan rakyat ‘’pemberi mandat.’’
Dengan kalkulasi popularitas dan kualitas untuk menjadi kandidat (yang menjadi alasan sosok itu dipilih oleh partai untuk didukung) diharapkan suara rakyat mejadi lebih bermakna. Proses politik yang seperti ini akan membawa konsekuensi bahwa calon yang terpilih, harus menunjukkan loyalitas pada rakyat. Jika hal ini diabaikan, maka karir politiknya akan pupus.
Di sisi lain, popularitas ini harus diukur lebih realistis, dan tidak bisa dimanipulasi dengan survei pesanan yang mahal. Sebab, faktor dukungan keuangan sudah bukan menjadi yang utama, setidaknya sama pentingnya dengan faktor popularitas calon. Ini akan mendorong terciptanya atmosfer pemilihan pemimpin yang lebih fair.
Dalam iklim ini, seseorang, meskipun cukup kaya, juga lebih baik ‘’bercermin’’ lebih dulu sebelum menjadi calon kepala daerah, ketimbang hanya membuat kegaduhan politik. Sebab, tentang popularitas, ini juga berarti bagaimana kepala daerah terpilih tampil menjadi pemimpin sesungguhnya bagi rakyat, dan bekerja melayani rakyat (bukan menjadi penguasa).
Partai Terbuka vs Politik Dinasti
Tantangan terbesar partai politik kali ini adalah masalah kaderisasi. Banyaknya kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat (di daerah maupun di pusat) yang terlibat kejahatan korupsi adalah masalah serius kaderisasi di Parpol. Apalagi, sejumlah kasus korupsi melibatkan pimpinan atas Parpol.
Hambatan terbesar dalam kaderisasi, selain karena platform partai yang tidak jelas atau hanya merupakan dokumen tanpa makna, adalah kecenderungan adanya praktik ‘’politik dinasti’’ dalam partai. Partai seperti ‘’properti pribadi’’ yang diwariskan kepada keturunan dan kerabat.
Sejumlah partai mungkin mengklaim diri cukup terbuka terhadap kader dari luar, namun dalam praktik, posisinya sangat bergantung pada keterikatannya dengan firgur sentral. Kalau tidak demikian, kader ‘’luar’’ hanya akan menjadi kader pinggiran.
Praktik politik dinasti ini yang menjadikan Parpol makin ‘’tertutup’’ terhadap kader baru dari luar yang sebenarnya cukup berkualitas, tetapi didominasi ‘’kader jenggot’’ (istilah pada Orde baru yang berarti kader yang berakar ke atas ). Krisis kader ini setidaknya terasa di kalangan partai dalam mencari calon untuk Gubernur Jakarta, dan tercermin pada masih banyak calon independen di sejumlah daerah.
Namun ada hal yang positif jika parpol kemudian membuka cakrawala untuk melihat figur di luar partai, ketimbang memaksakan calon dari partai sendiri yang sebenarnya elektabilitasnya rendah. Dan hal ini diharapkan mendorong reformasi dalam tubuh Parpol. Ini sekaligus sinyal bahwa Parpol yang masih didominasi budaya dinasti, akan semakin terseok-seok dan ketinggalan.
Jika perubahan ini terjadi dan makin nyata, kita bisa berharap proses politik semakin berkualitas. Kualitas itu antara lain pada dampak perubahan dengan meninggalkan kampanye yang mengaduk-aduk kebencian dan perbedaan identitas (etnisk dan agama), dan lebih mengangkat isu kesejahteraan dan keadilan.

Tembakan Pertahanan Udara di Isfahan, Iran, Belum Jelas seba...
TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Serangan pesawat tak berawak Israel terhadap Iran menyebabkan pasukan Iran ...