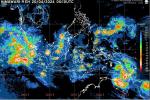Bincang Senja: Mulai Intoleransi di Jogja hingga Kasur Tua
YOGYAKARTA, SINARHARAPAN.COM - WS. Rendra pernah berkata, “Jogja itu ibaratnya seperti kasur tua”. Ungkapan inilah yang kembali digunakan oleh Hairus Salim dari LKis ketika mengawali pembicaraan dalam Bincang Senja bertajuk “Masa Depan Keberagaman Yogyakarta”.
Entah apa yang saat itu terlintas di benak Rendra sehingga mengatakan Jogja ibaratnya seperti “kasur tua”, namun bagi Hairus Salim, yang namanya “kasur tua” itu pasti tidak enak. “Kasur tua itu pasti atos (Jawa:keras),” demikian ungkap Hairus Salim.
Hairus Salim tak bicara seorang diri di senja itu. Pasalnya, ada tiga pembicara lain, yaitu Pendeta Indianto (Rumah Pirukun), Elga Sarapung (Dian – Interfidei), dan Muhammad Subkhi Ridho (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah). Keempat pembicara ini hadir untuk berdialog dan bertukar pemikiran dalam bingkai keberagaman di acara Bincang Senja yang digelar pada Kamis (30/1) di Kedai Gendhong, Jalan Sorowajan Baru No. 16, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Bincang Senja merupakan sebuah acara yang muncul sebagai wujud keprihatinan akan aksi kekerasan dan intoleransi yang mulai marak belakangan ini di Yogyakarta. Beberapa komunitas, seperti Jaringan Gusdurian, Our Indonesia, dan Komunitas Makaryo yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta, akhirnya mengemas sebuah dialog dengan tujuan untuk mengajak dan mengupayakan agar Yogyakarta dapat tetap damai dalam keberagaman.
Sekitar pukul 15.30 WIB, acara yang dipandu oleh Pedro Indarto dan dihadiri oleh puluhan aktivis lintas komunitas ini akhirnya dimulai. Sebagaimana diketahui, Pedro Indiarto adalah ketua aksi damai, “Partai Boleh Beda Jogja Tetap Damai” yang dihelat di perempatan Tugu Jogja pada Sabtu, 18 Januari 2014 silam. Bincang senja ini merupakan follop up dari aksi “Partai Boleh Beda Jogja Tetap Damai”.
Mengawali dialog, Muhammad Subkhi Ridho dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah menyampaikan pemikiran tentang adanya pergeseran dari esensi toleransi. “Arti toleransi akhir-akhir ini mulai direduksi dengan cara yang sangat sempit, yaitu yang penting tidak ada kekerasan fisik. Padahal arti toleransi itu sendiri dapat lebih luas, misalnya spanduk ‘Syiah bukan Islam’ yang terpampang akhir-akhir ini di Jogja sebenarnya adalah wujud intoleransi. Selain itu, spanduk caleg juga bisa jadi merupakan upaya pengkotak-kotakan, misalnya spanduk yang bertuliskan, “Putera asli Bantul”. Hal ini bisa menjadi bias karena memungkinkan adanya mengkotak-kotakkan antara orang asli Bantul dan bukan Bantul.”
Bagi kader Muhammadiyah ini, branding Kota Yogyakarta pada 2002-2003 yang digaungkan oleh Pemkot Yogyakarta melalui wali kotanya saat itu, Herry Zudianto sebagai Jogjakarta The City of Tolerance, kini mulai pudar. Memudarnya slogan ini, salah satunya diakibatkan karena orang masih alergi terhadap pluralisme sehingga muncul stigma negatif terhadap kaum pluralis yang mencoba untuk lebih menghargai arti keberagaman.
Degradasi sikap intoleransi pada masyarakat Yogyakarta ini pula yang menjadi sorotan Pendeta Indianto. Pria yang mendirikan komunitas Rumah Pirukun ini mencoba menelisik sikap intoleransi dari kacamata kebudayaan.
“Tahun 90-an, slogan ‘Yogyakarta Berhati Nyaman’ benar-benar terealisasi. Buktinya, ketika saya mau menyeberang di Malioboro, semua kendaraan berhenti. Bahkan saya sampai munduk-munduk (Jawa: membungkuk) kepada para pengemudi.
"Namun sekarang perilaku intoleransi justru yang sering kita temukan di jalan raya. Perilaku saling mengalahkan, tidak memperhitungkan orang lain yang berada di jalan raya, siapa cepat dia dapat, dan siapa nekat dia yang menang.
"Dulu ketika saya melanggar aturan lalu lintas, misalnya melawan arus, maka saya hanya diperingatkan, tidak langsung ditilang seperti sekarang. Kini, orang semakin tidak peduli dengan orang lain.
"Aparat penegak hukum juga tidak memberikan pembinaan, melainkan langsung penindakan. Artinya, sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai,” demikian disampaikan oleh Pendeta Indianto.
Menurut Pendeta Indianto, pada tataran analisis budaya terjadi pergeseran nilai pada masyarakat Yogyakarta, jika dibandingkan dengan kebudayaan (kebiasaan) yang ada pada tahun 90-an dengan 2000-an. Ekspresi dari pergeseran nilai, di mana individualisme, primordialisme yang didasari agama, suku, golongan, terekspresikan dalam tindakan konkret.
Arus budaya kekerasan yang belakangan ini mulai marak di Yogyakarta adalah ekspresi rusaknya, minimal, bergesernya tata nilai, yaitu tindakan saling mengalahkan atas nama agama, golongan, dan komunitas. Kasus nyata dari budaya kekerasan ini semisal kasus penyerangan di LP Cebongan yang melibatkan oknum Kopassus.
“Sistem nilai yang tampaknya mulai dirusak oleh individualisme, primordialisme, termasuk SARA, harus kita perangi dengan tindakan damai, tindakan kasih,” demikian Pendeta Indianto memberikan solusi.
Lain halnya dengan Pendeta Indianto yang menganalisa lewat frame budaya, Hairus Salim dari LKis mencoba menelaah lebih luas lagi untuk mencari solusi lewat panggung nasional. Menurut Hairus Salim, kekerasan yang terjadi belakangan ini merupakan imbas dari gerakan reformasi yang tak terarah. Satu contoh jelas yang tergambar di panggung nasional adalah agenda keagamaan.
“Waktu zaman Orba, rezim politik mengatur agenda keagamaan. Politik menjadi atasan dari dinamika keagamaan. Namun, usai Pak Harto jatuh, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu dinamika keagamaan menentukan arah perpolitikan. Contohnya adalah keberadaan MUI yang notabene merupakan suatu lembaga non negara, namun kini keberadaannya justru menentukan arah perjalanan negara. Saya melihat tujuan dari hal tersebut adalah adanya upaya ingin menyeragamkan suatu pandangan keagamaan, lebih sempit lagi pandangan Islam tertentu,” demikian disampaikan oleh Hairus Salim.
Program pokok untuk menyeragamkan pandangan (baca: Islamisasi) inilah yang membuat kelompok tersebut senantiasa memiliki inisiatif. Alhasil, menurut kacamata umum, kelompok ini adalah kaum protagonis. Di sisi lain, kaum pluralis yang bereaksi terhadap penyeragaman ini senantiasa dianggap sebagai pihak antagonis karena terus menerus terlambat untuk mengantisipasi. “Sekarang kita tidak bisa jika hanya bereaksi. Jika kita ingin terlihat protagonis, maka kita harus berinisiatif terlebih dahulu”.
Terkait dengan inisiatif tersebut, kaum pluralis dalam waktu dekat harus mengantisipasi datangnya Pemilihan Umum (Pemilu). Namun untuk jangka panjang, pluralis harus mengantisipasi kota Yogyakarta ini. “Jogja akan menjadi kota urban karena kondisi saat ini mulai mengarah ke sana. Ketakutan saya, Jogja sebagai The City of Tolerance akan berubah menjadi kota urban alias intoleran,” ucap Hairus Salim.
Menyambung paparan Hairus Salim, Elga Sarapung menyoroti suatu kenyataan di Indonesia, bahwa kini negara hanya mengikuti fatwa. “Inilah kenyataan dan kesalahan besar. Negara mengikuti agama (dalam hal ini MUI). Sekarang mulai ada fatwa tentang Ahmadiyah. Kita harap fatwa Syiah tidak keluar,” ucap aktivis dari Dian-Interfidei ini.
Di sisi lain, Elga juga menyoroti tentang ketidakadilan terkait dengan e-KTP. Elga mencontohkan tentang poin agama yang tertera di KTP. “Masyarakat di Kalimantan yang banyak menganut Kaharingan diperbolehkan untuk menulis kepercayaan tersebut di KTP. Namun, penulisan tersebut hanya berlaku secara lokalitas, karena jika telah dimasukkan ke dalam E-KTP, maka tidak ada ruang untuk Kaharingan, melainkan hanya diberikan pilihan sebagai Hindu Kaharingan. Ini bukan hanya soal ketidakadilan, tetapi memakai teologi keagamaan untuk menjustifikasi dalam rangka kehidupan berbangsa,” demikian disampaikan oleh Elga Sarapung.
Kenyataan ini jika dibiarkan tentu akan semakin menyempitkan ruang keberagaman. Hal yang lebih terlihat lagi dengan pembiaran ini adalah pemakaian frame mayoritas-minoritas dalam rangka melanggengkan kekuasaan. “Posisi negara dan kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalamnya hendaknya tetap menjadikan nilai pluralitas sebagai patokan dalam menentukan kebijakan,” ungkap Elga.
Usai para pembicara memaparkan pemikiran, dilakukan dialog dengan para aktivis. Para aktivis melontarkan pemikiran serta pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara. Beberapa pertanyaan tersebut, semisal Aan dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga menyampaikan pemikiran bahwa faktor utama kesulitan untuk menerapkan pluralisme di Inodensia adalah masalah ekonomi.
Hadianto dari Puskat Jogja Kotabaru menyampaikan pemikiran bahwa muara dari kekisruhan yang terjadi di Indonesia adalah keserakahan manusia an sich kapitalisme sehingga menghilangkan nilai. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah menempuh jalur pendidikan yang bisa menanamkan pendidikan nilai dan arti kemajemukan sejak dini.
Menanggapi pemikiran para aktivis sekaligus sebagai statement akhir, Muhammad Subkhi Ridho menyatakan bahwa terkait dengan isu pluralisme (multikulturalisme), maka kita harus masuk ke konteks pemberdayaan ekonomi warga atau rakyat kecil, misalnya melalui semangat Go Green, seperti bank sampah, penanaman pohon, dan lain-lain.
“Ranah inilah yang harus kita garap karena bebas nilai. Tidak ada yang peduli dengan ini sampah milik siapa atau pohon beragama apa,” ujar Muhammad Subkhi Ridho.
Pendeta Indianto sepakat dengan solusi pendidikan untuk mengatasi persoalan pluralisme. “Hanya pada pendidikan nilai-nilai yang luhur, seperti solidaritas, kita bisa menghormati masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur,” kata Indianto.
Pendeta Indianto juga memberikan solusi untuk masuk ke dalam gerakan besar (arus besar) anti kekerasan, deradikalisme, dan multikulturalisme dengan menggarapnya melalui jejaring. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka sekat, dikotomi, pengkotak-kotakan antarumat beragama maupun antara intern agama bisa dirobohkan.
Di sisi lain, Elga Sarapung memberikan solusi agar kita dapat lebih percaya (trust) kepada orang lain. “Kepercayaan tersebut bisa menjadi kekuatan bersama untuk membangun bangsa. Kita memerlukan ruang untuk membangun itu, seperti kampus, gereja, kedai, masjid, dan lain sebagainya. Kita perlu menciptakan sebanyak mungkin ruang bersama untuk melatih diri kita dalam menghargai perbedaan. Ciptakanlah ruang-ruang bersama itu. Dan seringlah berkumpul di ruang-ruang itu”.
Hairus Salim di sesi akhir pernyataannya lebih menyoroti Yogyakarta yang kini pelan tapi pasti mulai berubah ke arah kota urban yang intoleran. Keadaan kota Yogyakarta yang sekarang ini berbeda dengan puluhan tahun silam. Yogyakarta kini mulai menampakkan sisi ketidaknyamanannya. Banyak degradasi nilai yang semakin hari, semakin jelas terlihat.
Satu hal yang jelas terlihat di Yogyakarta sekarang ini adalah desa-desa di Yogyakarta kini mulai menjadi desa urban. Namun, meskipun mulai tidak nyaman, sesuai dengan lead di atas yang diibaratkan oleh Rendra sebagai “kasur tua”, kita harus terus berusaha membuat Yogyakarta tetap nyaman.
Hidup bersama sungguh bahagia/ Selalu damai dengan sesama/ Walaupun beda suku agama/ Kita satu adanya/ Assalamu’alaikum/ Shalom/ Santi/ Salam oh wassalam/ Kita satu adanya. (Sebuah lagu yang jamak dinyanyikan oleh aktivis pluralis)
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja

Bertemu Herzog, Menlu Inggris: Jelas Israel Akan Tanggapi Se...
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengatakan jelas bahwa Israel...