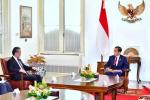HUT 71 Kemerdekaan: Renungan Suci Tentang Kebangsaan
Setelah 71 tahun merdeka, apakah kita masih merasa sebagai satu bangsa? Tetapi apakah kebangsaan itu? Apa yang mengikat kita sebagai satu bangsa?

SATUHARAPAN.COM - Memasuki usia 71 tahun kemerdekaan, saya ingin mengajak semua anak bangsa melakukan perenungan suci mengenai kebangsaan kita. Apa yang dimaksud? Perenungan adalah kontemplasi mendalam tentang makna keberadaan kita, tentang tujuan hidup kita, dan seterusnya. Mengapa suci? Karena kita melakukannya di hadirat Tuhan. Kita sadar bahwa di hadirat-Nya tidak boleh kita menyembunyikan apapun.
Dini hari menjelang 17 Agustus setiap tahun, ada kebiasaan melakukan renungan suci di TMP Kalibata. Ini bermakna sangat mendalam. Kita melakukan perenungan mendalam tentang keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia bukan saja di hadapan Tuhan, melainkan juga di depan para pahlawan yang telah mendahului kita. Masihkan kita setia kepada cita-cita perjuangan mereka ketika mereka membentuk dan membangun bangsa ini, ataukah kita telah mengkhianati cita-cita suci mereka itu? Itulah makna suci yang sekali gus berimplikasi kita sangat serius dengan keberadaan kita sebagai bangsa.
Tetapi apakah bangsa sesungguhnya yang terhadapnya kita melakukan perenungan suci sekarang? Tentu saja banyak defenisi bisa diajukan. Namun dalam kaitan dengan hal menjadinya kita sebagai bangsa, saya ingin mengutip Bung Karno. Sebelumnya perlu dicatat, Indonesia sebagai bangsa adalah sebuah novum di atas ranah sejarah dunia. Sebelumnya tidak ada bangsa Indonesia. Yang ada adalah bangsa-bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Toraja, bangsa Madura, bangsa-bangsa yang mendiami kepulauan Sunda Kecil, dan seterusnya.
Maka adalah sebuah keajaiban bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 itu, bukan saja kemerdekaan, melainkan keberadaan sebuah bangsa diumumkan ke seluruh dunia. Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu itu tampil mewakili bangsa Indonesia.
Bung Karno dalam pidatonya yang terkenal pada 1 Juni 1945 di depan Dokuritsu Syunbi Tyoosakai, dengan mengutip Otto Bauer di dalam bukunya Die Nationalitaetenfrage berucap: “Was ist eine Nation? Eine Nation ist eine aus Schiksalgemeinschaft erwaschene Charactergemeinschaft”. [Apakah bangsa? Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib]. Beliau juga mengutip Ernst Renan, “le desir d’etre ensemble?” Yang menjadi bangsa, dengan mengutip Renan adalah “satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu”.
Ada dua elemen penting dalam kutipan-kutipan tersebut yang ditekankan Bung Karno, yaitu “persatuan perangai karena persatuan nasib” dan “kehendak untuk bersatu”. Bangsa-bangsa di Nusantara ini telah mengalami nasib bersama di bawah imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan Jepang selama ratusan tahun, dan karena itu terbentuklah karakter mereka untuk bersatu. Hal itu hanya terjadi karena mereka mau bersatu. Ada rasa kebersamaan dan kesenasiban.
Maka guna merawat rasa kebangsaan inilah Bung Karno mengusulkan Pancasila yang disebutnya Philosofische grondslag [dasar filosofis] dari negara yang bakal didirikan itu. Kata Bung Karno: “Philosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”
Pertanyaan kita sekarang, setelah 71 tahun Indonesia Merdeka, masihkah kita mempunyai kesatuan karakter untuk bisa merasakan kebersamaan dan kesenasiban? Masihkah ada hasrat untuk bersatu, atau kita malah cenderung merusak persatuan kita baik langsung atau tidak langsung?
Kita mengakui, dalam perjalanan panjang ini bangsa kita telah mengalami pasang-surat, turun-naik rasa sebagai bangsa. Kita telah dan sedang mengalami 3 rezim (Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang Orde Refomasi). Dalam perjalanan itu banyak kemungkinan terjadi. Kendati demikian, mestinya ada yang tetap, yang tidak boleh tergoyahkan yaitu rasa kebangsaan itu. Kalau ini terguncang, kita tidak lagi mempunyai dasar, dan dengan demikian Indonesia bisa runtuh berantakan dan kemudian hanyalah tinggal nama saja.
Pada waktu saya menulis artikel ini secara kebetulan saya temukan di medsos sebuah meme dari Emha Ainun Najib (Cak Nun). Meme itu berbunyi demikian: “Kalau sudah dapat ilmu gayamu kebarat-baratan, kalau sudah merasa alim, gayamu kearab-araban. Jowomu endi?” Meme ini rasanya mewakili banyak ketidakpuasan di antara kita menyiasati perkembangan kepribadian bangsa kita. Masihkah kita merasa sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kejayaan dan kebanggaan atas segala warisan yang kita peroleh? Ataukah kita sedang mengidap rasa rendah diri (minderwaardigheidskompleks) akut di hadapan bangsa-bangsa sedunia?
Sebagai contoh, kita gemar sekali melabel berbagai hal di negeri ini dengan bahasa Inggris, seakan-akan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Maka di mal-mal, gedung-gedung, bahkan gedung-gedung pemerintah intervensi bahasa Inggris itu sangat terasa. Tentu saja saya tidak bermaksud untuk tidak mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan dunia. Tetapi kalau bahasa Indonesia sudah menjadi asing di negerinya sendiri, ini harus serius ditangani, sebab ini menyangkut rasa kebangsaan kita. Lagi pula ini menabrak Konstitusi RI yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Dalam cara berpakaian kita pun cenderung mengecilkan kepribadian kita yang justru oleh dunia digandrungi. Kaum perempuan di awal-awal era kemerdekaan sangat anggun dan bangga memakai kain kebaya. Rasanya sekarang ini sudah jarang terlihat, kecuali di upacara hari Kartini.
71 tahun rasanya juga belum cukup menyadarkan bangsa kita untuk tidak lagi membuat dikhotomi-dikhotomi antara misalnya “pribumi” dan “non-pribumi”, “Islam” dan “non-Islam”, “Jawa” dan “Luar-Jawa”, dan seterusnya. Sebenarnya kia sudah lelah dengan perilaku-perilaku tidak nasionalis ini. Contoh paling mutakhir, dalam rangka pilkada DKI misalnya, yang ditonjolkan untuk dikritisi bukanlah kebijakan dan program sang inkamben gubernur, melainkan golongannya, bahwa ia bukan pribumi dan bukan Islam.
Beberapa hari lalu misalnya diselenggarakan di Gedung Joang 1945 sebuah seminar menolak Ahok sebagai cagub DKI. Yang ditonjolkan adalah, kendati Gubernur Ahok terpilih kembali, ia tetap tidak syah menurut Syariat Islam. Karena itu ia harus ditolak karena dia adalah pemimpin kafir. Adalah sebuah ironi sejarah bahwa seminar semacam ini diselenggarakan di sebuah gedung sangat bersejarah yang justru menjunjung tinggi kebhinekaan. Itulah gedung yang di dalamnya Sumpah Pemuda yang melegende itu diucapkan pada 1928. Maka mestinya rasa kebangsaan kita dibangkitkan dan direnungkan secara khikmad menghadapi berbagai perkembangan seperti ini. Tentu saja di alam demokrasi ini setiap orang bebas menyampaikan pendapat dan melakukan apa saja. Namun demikian tetaplah diperhatikan bahwa ada kesepakatan-kesepakatan nasional yang tidak boleh seenaknya ditabrak begitu saja.
Cita-cita proklamasi yang menekankan kegotongroyongan bangsa kita juga mengalami berbagai degradasi oleh adanya berbagai intrik politik yang hanya menekankan pencapaian kekuasaan dengan segala cara, dan bukan demi kemaslahatan bersama. Maka drama yang dipertontonkan di depan kita adalah perjuangan-perjuangan politik minus etika dan moral. Bahkan terdapat kecenderungan etika dan moral ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan politik, bukan sebaliknya, politik dibimbing oleh etika dan moral. Maka ketika seseorang menggenggam kekuasaan dalam tangannya, ia tidak mampu mempergunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan bersama. Ia cenderung mempergunakannya bagi kepentingan sendiri mau pun kelompoknya.
Banyaknya kepala-kepala daerah yang ditangkap KPK misalnya, adalah contoh bagaimana penyalahgunaan kekuasaan itu begitu menonjol. Semua ini tidak memberi contoh positif bagi bangsa kita, khususnya generasi muda kita. Mereka tidak melihat apa-apa yang bisa ditiru dari para orang tua mereka bagi pemupukan rasa kebangsaan. Kalau dalam berbagai tindakan itu penghargaan terhadap orang lain mendapat porsi amat kecil, maka generasi muda juga tidak merasa perlu menghargai orag-orang lain. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh tindakan-tindakan pemukulan guru bahkan pembunuhan kepada seorang dosen yang dilakukan oleh anak didik sendiri. Inilah contoh buram dunia pendidikan kita. Hal-hal ini sesungguhnya dicontoh dari sikap-sikap premanisme yang diragakan oleh orang-orang tua yang mestinya menjadi patron yang baik.
Pertanyaan inti dari semuanya ini adalah, masihkah kita menghayati nilai-nilai Pancasila yang merupakan warisan paling berharga dari para pendahulu kita? Kita terlalu enteng menilai bahwa Pancasila telah gagal hanya karena Orde Baru pernah mempergunakannya secara keliru guna mempertahankan kekuasaan mereka yang penuh dengan KKN. Intisari dan saripati kebangsaan itulah yang ditubuhkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Maka meninggalkan Pancasila sama artinya membunuh diri bagi bangsa ini.
Dirgahayu Bangsa Indonesia!
Penulis adalah teolog, mantan Ketua Umum PGI 2009 – 2014
Editor : Trisno S Sutanto

Tembakan Pertahanan Udara di Isfahan, Iran, Belum Jelas seba...
TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Serangan pesawat tak berawak Israel terhadap Iran menyebabkan pasukan Iran ...