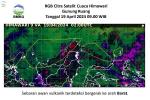Ke Mana Anak dengan HIV Harus Sekolah?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Lagu-lagu anak terdengar gaungnya di Minggu pagi itu dari sebuah ruangan. Salah satu lagunya berjudul Pelangi-pelangi. Di dalam ruangan itu, sejumlah balita bermain dengan balok-balok dan melempar bola dengan ditemani orang tua mereka.
Di luar ruangan, terlihat orang-orang dewasa bergantian menggendong bayi dan bercengkerama dengannya. Bayi itu pun menanggapi dengan senyuman gembira saat digendong mereka.
Mencoba bertanya kepada salah satu dari mereka tentang usia bayi itu, ia menjawab, "Usianya satu tahun empat bulan," sambil menambahkan, "Ibunya belum lama meninggal karena HIV." Bayi itu juga hidup dengan HIV.
Hari Minggu pagi itu merupakan acara spesial bagi anak-anak dengan HIV. Mereka datang ada yang bersama orang tuanya, kerabat lain, atau perawat. Sekilas tidak tampak perbedaan antara anak HIV dan yang bukan HIV.
Hari (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu anak yang hadir di acara itu. Pelajar SMP yang menyukai sepakbola itu mengaku sudah setahunan lebih menghadiri acara itu. Dia sangat senang bisa ikut hadir.
Acara itu terbagi dalam beberapa kelompok usia. Di ruangan yang terdengar lagu-lagu anak dan di dalamnya bayi bermain dengan balok-balok dan melempar bola itu merupakan kelas bayi bermain. Itu merupakan kelas untuk anak paling kecil sampai usia lima tahun. Kelas itu bertujuan untuk merangsang motorik.
Lalu ada kelas untuk anak usia lain yang diisi dengan menari, pemutaran film, diskusi, dan lain-lain. Untuk para orang tua dan perawat ada kelas terkait pola pengasuhan, psikososial, dan relaksasi. Kelas itu dibutuhkan mengingat orang dengan HIV tidak bisa sembarangan curhat.
Anak dengan HIV Juga Berhak atas Pendidikan
Laporan Kementerian Kesehatan per Desember 2019 menyebutkan anak dengan HIV ada lebih dari 10.000 anak, meliputi rentang usia 0-14 tahun. Lalu bagaimana situasi anak-anak ini di pendidikan?
Menilik peristiwa sebelumnya. Pada 2019 ada 14 anak di Solo, Jawa Tengah, yang dikeluarkan dari sekolah. Sebelumnya pada 2018, ada tiga anak di Samosir, Sumatera Utara, juga diusir karena statusnya dengan HIV diketahui.
Retno Listyarti menyebutkan pantauannya sejak menjabat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan pada 2017. "Ada dua kasus yang menjadi pengawasan saya sebagai komisioner KPAI. Yaitu kasus anak-anak dengan HIV yang ditolak belajar di sekolah formal. Yakni di kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dan Solo, Jawa Tengah.”
"Pemenuhan hak pendidikan anak di sekolah formal yang kemudian terpenuhi ada di kota Solo. Sedangkan anak-anak dengan HIV di Kabupaten Samosir hanya diberikan pilihan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau homeschooling," tuturnya.
Retno Listyarti menyampaikan, anak-anak dengan HIV berhak atas pendidikan seperti halnya anak-anak lainnya.
"Dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan tiap-tiap warga negara dijamin hak atas pendidikannya oleh negara. Konstitusi menyebutkan tiap-tiap orang. Jadi siapa pun dia, sakit atau sehat, kaya atau miskin, selama menjadi warga negara Indonesia, maka haknya atas pendidikannya harus dipenuhi negara. Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara dalam keadaan apa pun. Termasuk anak-anak dengan HIV."
Hal senada juga dikatakan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana. Setiap anak berhak atas pendidikan. Termasuk anak-anak dengan HIV.
Sejauh Mana Stigma dan Diskriminasi Ini?
Terkait adanya diskriminasi dan stigma yang menimpa anak dengan HIV selama ini di dunia pendidikan, mengantar langkah bertanya ke lembaga yang konsern mendampingi anak dengan HIV, yaitu Lentera Anak Pelangi (LAP).
Di LAP, Manajer Advokasi, Natasya Sitorus, menuturkan pengalamannya mendampingi anak dengan HIV.
"Beberapa anak tidak secara lisan diminta keluar. Tetapi ada desakan dari orang tua murid. Kemudian juga ada upaya dari sekolah. Tetapi, tidak dikatakan langsung anak ini harus keluar," ia menjelaskan.
Jumlah kasus stigma dan diskriminasi yang menimpa anak-anak dengan HIV di pendidikan itu kecil, tetapi tidak bisa dikatakan rendah. Diskriminasi tidak muncul bisa jadi karena selama ini pihak sekolah tidak mengetahui. "Sebagian besar memilih merahasiakan status HIV mereka sehingga pihak sekolah tidak mengetahui kalau anak-anak ini HIV."
Pada satu sisi ada ketakutan ketika pihak sekolah mengetahui anak-anak dengan HIV menjadi peserta didiknya maka pihak sekolah tidak dapat menerima.
"Kalau sekolah sudah mengetahui dan tetap menerima, artinya itu tidak ada diskriminasi," katanya. "Ada kasus-kasus ketika sekolah mengetahui tetapi mereka tetap tidak mau mendiskriminasi. Karena menurut mereka informasinya sudah cukup. Menurut mereka anak itu tetap berhak untuk sekolah."
Diskriminasi juga diakibatkan ketidaktahuan, karena masih ada yang berpikir bahwa kontak sosial dapat menularkan HIV. Maka ketika informasi tentang HIV diketahui dengan baik, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi.
Stigma atas HIV pun dijumpai saat LAP melakukan penyuluhan. Ada yang berpandangan HIV itu merupakan akibat dari dosa, bentuk hukuman spiritual, akibat menjadi LGBT, dan sebagainya.
"Ada saja diskusi tentang isu-isu itu. Namun, kami coba menjelaskan, siapa pun pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidup mereka. Termasuk orangtua dari anak-anak ini. Tetapi anak-anak ini juga tidak bisa memilih dari mana mereka dilahirkan. Tidak sepantasnya juga anak-anak ini didiskriminasi."
Pendidikan untuk Semua Anak
Mawar (bukan nama sebenarnya) sangat bangga menceritakan bakat anaknya yang berusia 13 tahun.
"Dia biasanya suka bereksperimen... Lihat di YouTube tutorial lalu dia mencoba caranya seperti apa? Mobil-mobilan yang rusak dia perbaiki," katanya.
"Cita-citanya menjadi pilot. Nilai ilmu pengetahuan alamnya bagus. Anaknya bertanggung jawab. Misalnya ada PR, langsung dikerjakan. Padahal, kalau anak laki-laki biasanya cuek dengan tugas-tugas sekolah."
Anaknya diketahui HIV saat usia 4 bulan. Mawar pun mengaku cemas dengan diskriminasi atas anak-anak dengan HIV. Karena itu, dia merahasiakan statusnya dengan HIV.
Situasi menolak kehadiran anak dengan HIV seperti di Samosir, Sumatera Utara, pasti akan terus terjadi ketika tidak dikenai sanksi yang jelas. Orang-orang di daerah lain bisa ikut-ikutan menolak kehadiran anak dengan HIV di sekolah mereka. Anak-anak dengan HIV diperlakukan tidak adil karena tidak bisa menempuh pendidikan layaknya anak lain.
Pada sisi lain, rasa trauma juga dialami anak akibat penolakan atau tidak diinginkan. “Sebagian anak-anak ini tidak mengetahui kalau mereka HIV,” kata Natasya Sitorus.
Status sekolah ramah anak harusnya juga bisa menjadi salah satu indikator dari kota layak anak. "Predikat-predikat itu harusnya bisa untuk menilai apakah di sekolah ini tidak terjadi bullying, tidak pernah terjadi kekerasan, apakah sekolah ini punya akses yang baik untuk anak-anak dengan disabilitas.”
Banyak upaya dilakukan LAP untuk mengikis stigma, diskriminasi, dan menciptakan akses pendidikan bagi anak dengan HIV. Selain audiensi ke Dinas Pendidikan, kampanye di media sosial, penyuluhan, dan lain-lain. Sempat juga ingin bersurat ke Presiden Joko Widodo.
LAP juga pernah mempetisi Menteri Pendidikan saat dijabat Anies Baswedan. LAP meminta sanksi tegas kepada sekolah yang membiarkan diskriminasi. "Kami tidak mengatakan sekolah yang mendiskriminasi. Kami mengatakan sekolah yang membiarkan terjadinya diskriminasi. Artinya baik itu gurunya, siswanya, orang tua dari sekolah tersebut itu harus diberikan tindakan yang tegas."
Karena Undang-Undang sudah jelas. "Undang-Undang Pendidikan Nasional nondiskriminatif. Undang-undang Perlindungan Anak juga jelas. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga jelas. Tetapi bagaimana penerapannya di lapangan ketika hak anak dilanggar? Siapa yang akan turun dan menyatakan bahwa ini adalah salah dan ini sanksinya?" pungkas Natasya Sitorus.
Editor : Sotyati

Israel Mengatakan Akan Membalas Iran, Inilah Risiko-risiko Y...
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Israel bersumpah untuk membalas Iran, berisiko memperluas perang bayangan...