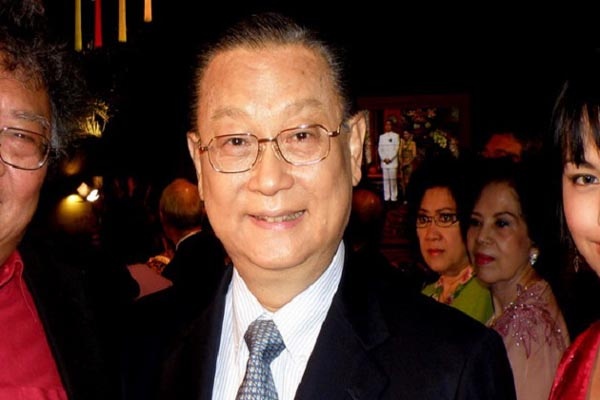Kebudayaan Merdeka

SATUHARAPAN.COM – Kalau kebudayaan itu kita artikan sebagai proses sengaja manusia yang melibatkan totalitas dirinya: nalar, intuisi dan fisik atau segala sumber daya yang dia miliki untuk bertumbuh dan berkembang secara kualitatif, maka kebudayaan itu pada dasarnya harus bermakna ‘merdeka’. Kebudayaan harus dimengerti sebagai strategi manusia dan komunitasnya untuk membebaskan diri dari segala yang menghambat dan mengikatnya untuk berkembang. Maka, sekali lagi ‘(ke)budaya(an) adalah tentang gerakan untuk ‘merdeka’.
(Ke)merdeka(an) sebagai Strategi Kebudayaan
Tapi, tidak semua apa yang kita namakan sebagai ‘gerakan merdeka’ itu memiliki makna bagi manusia dan komunitasnya untuk ‘bertumbuh’ dan ‘berkembang’ secara kualiatif. Revolusi bersenjata yang fasis meskipun menamakan dirinya sebagai gerakan menuntut kemerdekaan, tapi setelah ‘merdeka’ itu diraih penindasan akan berulang dalam sebuah otoriterianisme. Pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan material, tentu tidak dapat disebut sebagai ‘gerakan merdeka’ untuk sebuah pemaknaan kesejatian hidup manusia dan komunitas. Kita sudah lihat dan rasakan bagaimana kapitalisme yang telah menyebabkan persaingan dan perang antar kelompok orang atau negara memperebutkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia
Maka, Pramoedya Ananta Toer dalam Jejak Langkah, dengan tokohnya Minke dalam novel itu harus berkata: “Di balik setiap kehormatan mengintip kebinasaan. Di balik hidup adalah maut. Di balik persatuan adalah perpecahan. Di balik sembah adalah umpat...”
Jangan-jangan “(ke)merdeka(an)” bukan jalan tengah. Sebab di sisinya yang sebelah, dan sangat dekat dengannya adalah penjajahan atau penderitaan (ketidakmerdekaan). Barangkali karena itulah sehingga Pram melanjutkan dialog Minke itu, “Maka jalan keselamatan adalah jalan tengah. Jangan terima kehormatan atau kebinasaan sepenuhnya. Jalan tengah—jalan ke arah kelestarian.”
Kebudayaan yang juga dapat dimengerti sebagai proses pengembangan peradaban adalah refleksi atas kehidupan yang terjajah. Kekuasaan yang bersumber dari superioritas ras, pengetahuan, agama, ekonomi dan ideologi negara telah melahirkan penindasan dan penjajahan. Sehingga, kemerdekaan dalam makna jalan untuk ‘bertumbuh’ dan ‘berkembang’ secara kualitatif adalah sebuah gerakan melestarikan hidup.
Kemerdekaan sebagai strategi kebudayaan – demikian kalau kita mengikuti maksud Cornelis Anthonie van Peursen mengenai kebudayaan – adalah sebuah proses membebaskan manusia dari kuasa-kuasa yang membatasi atau menjajahnya. Manusia yang terjajah adalah manusia yang dibatasi atau bahkan dimatikan pengetahuan, kreatifitas, serta ruang geraknya dalam berelasi. Penjajahan dalam bentuk dan bersumber dari apapun dapat mengubah manusia menjadi seperti zombie, makhluk yang fisiknya bergerak tapi jiwa, nurani, kreatifitas serta kebebasan berekspresinya mati.
Kebudayaan Merdeka
Lalu, apakah “Indonesia merdeka’, yang 17 Agustus lalu berusia 70 tahun itu sudah menjadi ‘kebudayaan’ bagi manusia-manusia Indonesia? Apakah ‘merdeka’ itu sudah menjadi kesadaran, pengetahuan, dan perjuangan bersama dalam keseharian sebagai sebuah kegiatan berkebudayaan? Apakah hal kemerdekaan itu sudah menjadi 'adat' dalam setiap dimensi hidupnya? Atau, jangan-jangan ‘Indonesia merdeka’ itu hanya takhayul tapi karena terus dirayakan setiap tahun maka seolah-olah ia telah menjadi kebenaran?
Hari-hari hidup manusia-manusia Indonesia sekarang ini, dengan gejala-gejala diskriminasi, pembatasan hak, dan bahkan kekerasan agaknya dapat memberi gambaran mengenai apakah merdeka itu sudah menjadi kebudayaan atau belum. Mari kita amati dan berefleksi mulai dari kehidupan kerja kaum buruh, petani dan nelayan. “Kerja sehari makan sehari”, saya kira tidak sebatas ungkapan kekecewaan biasa. Ungkapan ini dapat kita pahami lebih dalam sebagai sebuah refleksi ‘orang-orang kalah’, bahwa kerja itu hanya bermakna ‘hidup sehari’. Dan besok atau lusa, kembali akan menjadi hari-hari berat, atau bahkan kematian.
Itulah kemiskinan di tengah bangganya negara ini mengklaim diri ‘merdeka’. Kalau ‘kerja’ kaum buruh, nelayan dan petani tidak dapat membantu manusia ‘bertumbuh’ dan ‘berkembang’ sebagai strategi melestarikan kehidupannya, maka sesungguhnya kita masih dalam kondisi ‘terjajah’. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 harus diusahakan lagi sebagai strategi kebudayaan.
Lalu, kita amati dan refleksikan juga kehidupan ‘para pembesar’ di pusat-pusat kekuasaan. Apakah jabatan itu sudah dihayati sebagai bagian dari berkebudayaan? Korupsi masih menjadi persoalan besar birokrasi kita. Hari ini tampil di layar tv dengan stelan jas lengkap dan bicara penuh percaya diri, eh besok ditangkap KPK karena kasus korupsi. Maka, jadilah hidupnya mandeg di penjara bertahun-tahun. Padahal, si koruptor itu hidupnya tampak sangat agamis.
Agama dalam penghayatan dan praktik ternyata belum sepenuhnya dapat membebaskan manusia dari hasrat kaya dan berkuasa, apalagi membebaskan kehidupan bersama dari penjajahan kuasa politik dan pasar. Agama, bahkan cenderung ‘menjajah’ manusia: hidup dalam kemunafikan penampilan, kebencian terhadap yang lain dan menjadi salah satu sumber ketidaknyamanan hidup bersama.
Kebudayaan merdeka mari kita mengerti sebagai kesadaran kemanusiaan yang tinggi. Ia adalah strategi kebudayaan, di maka ‘(ke)merdeka(an) tidak sebatas slogan, tapi ia adalah gerakan kehidupan. Ia sebagai kerja aktif (ber)kebudayaan, di mana kreatifitas dan kebebasan mendapat jaminan. Kemerdekaan sebagai gerakan kehidupan (strategi kebudayaan) adalah kesadaraan bahwa kemanusiaan itu menemukan makna hakikinya ketika masing-masing orang dapat bersama-sama memperjuangkan, memelihara dan melestarikan kebebasan.
Penulis aktif di Mawale Cultural Center, Minahasa

167 Siswa SLTAK PENABUR Jakarta Lolos PTN Jalur SNBP 2024, S...
Jakarta, Satuharapan.com, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbduriste...