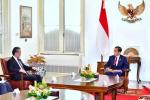Krisis Nduga: Bertaruh Nyawa Melahirkan Anak di Tengah Konflik Senjata

PAPUA, SATUHARAPAN.COM – Para perempuan di Nduga dan anak-anak mereka terpaksa bertahan di belantara di Pegunungan Tengah Papua, untuk menghindari konflik bersenjata antara TNI/Polri dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua, yang berlangsung selama delapan bulan terakhir. Bahkan, beberapa dari mereka terpaksa melahirkan di hutan.
Seorang bayi laki-laki menangis di pangkuan ibunya. Napasnya berat, sementara badannya yang demam, tidak ditutupi sehelai kain pun.
Sang ibu, Jubiana Kogeya, tampak kebingungan. Beberapa kali dia mencoba menenangkan anaknya dengan menyusuinya, namun tak setitik pun ASI keluar. Oleh sang ibu, bayi itu dinamai Pengungsi.
“Karena melahirkan dalam hutan, dalam pengungsian, jadi saya kasih nama Pengungsi,” jawab Jubiana ketika ditanya alasan anak keempatnya itu dinamai Pengungsi.
Pengungsi lahir sekitar empat bulan lalu, ketika ibunya dalam pelarian dari rumahnya di Distrik Mugi, untuk menghindari kontak bersenjata antara TNI/Polri dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua.
Awalnya, Jubiana yang saat itu hamil besar, enggan mengungsi. Sementara, suami dan ketiga anaknya kala itu sudah bersiap mengungsi.
“Pada saat penyerangan dan pembakaran di Distrik Yigi dan Yal itu, saya masih bertahan. Begitu terjadi di Mugi, itu baru mulai bergerak ke luar rumah,” tutur Jubiana kepada Ayomi Amindoni dari BBC News Indonesia, Jumat (2/8) silam.
“Saya melihat suami saya pegang anak-anak di kedua tangannya, akhirnya saya terpaksa ikut mengungsi. Saya dengar di Mugi sudah ada tentara, ada penembakan, pembakaran, akhirnya ke luar rumah, masuk ke hutan,” ujarnya.
Selama berhari-hari, Jubiana dan ketiga anaknya yang masih kecil harus menghadapi cuaca dingin pegunungan dan makan semacam tumbuhan paku yang tumbuh di hutan untuk asupan sehari-hari.
Hingga akhirnya sekitar April lalu, dia terpaksa melahirkan di hutan.
“Saya sendirian, tidak ada yang temani, (saya melahirkan) di bawah pohon,” kata Jubiana, sambil berupaya menenangkan Pengungsi yang terus menangis.
“Anak ini posisinya melintang (di perut), prosesnya hampir taruhan nyawa. Saya pikir anaknya sudah meninggal, karena ketika mau melahirkan saya tekan, saya atur sendiri, dia melintang, jadi saya atur. Saya pikir anak ini sudah meninggal,” dia mengungkapkan.
Berpindah Lebih Jauh ke dalam Hutan
Sejak dilahirkan April lalu, Pengungsi tidak pernah mengenakan baju. Ketika cuaca dingin menerjang, Jubiana hanya bisa memeluk anaknya erat dan menyelimutinya dengan anyaman daun pandan.
“Bikin tikar pakai daun pandan, lalu kasih alas dia, terus peluk dia,” tutur Jubiana.
Jubiana merupakan salah satu dari ribuan warga Nduga yang kini terpaksa harus mengungsi dari konflik yang berkecamuk di Nduga.
Pengungsi lain, Katarina Kogeya dan delapan anaknya terpaksa bertahan di hutan selama beberapa lama untuk menghindari kontak senjata di kampungnya di Distrik Yal.
“Tidak sempat bawa apa-apa. Bawa anak saja di tangan, sampai di hutan kami bikin tenda-tenda di hutan dari daun-daun. Anak-anak ini menangis minta makan karena tidak ada makan lagi.”
“Akhirnya harus pindah lagi dari tempat itu ke tempat yang jauh ke dalam hutan yang lebih rimba lagi.”
Sejak Juni silam, keduanya mengungsi di Distrik Ilekma di Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk menghindari konflik yang berkecamuk di Nduga sejak delapan bulan silam. Banyak di antara mereka, hingga kini masih bertahan di hutan.
Korban di Tanah Mereka Sendiri
Pegiat HAM yang mendampingi para pengungsi, Theo Hesegem, mengatakan, para pengungsi ini menjadi “korban di tanah mereka sendiri”.
“Mereka mengatakan kita takut dua-duanya karena dua-dua ini pegang senjata jadi kalau dua-dua ini pegang senjata dan terjadi baku kontak antara TNI dan OPM, masyarakat bisa jadi korban di tengah-tengah,” ujar Theo.
Eskalasi kontak senjata antara militer dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua terjadi setelah insiden penembakan belasan pekerja konstruksi Jalan Trans Papua pada Desember silam.
Selama delapan bulan terakhir, gelombang pengungsi tersebar ke beberapa wilayah di sekitar Nduga, bahkan beberapa di antaranya dilaporkan meninggal.
Namun, oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) Sebby Sambom, banyaknya pengungsi dan korban yang berjatuhan adalah sebagai “risiko dari perang”.
“Itu risiko dari perang. Itu bukan TPN yang usir tapi Indonesia yang masuk, jadi mereka takut Indonesia. Oleh karenanya tanggung jawab Pemerintah Indonesia, bukan TPN. TPN kan selalu tinggal dengan masyarakat, di kampung-kampung, tidak pernah ancam masyarakat, tidak pernah usir masyarakat. Mereka mengungsi karena kehadiran TNI/Polri dalam jumlah besar dan melakukan pembakaran rumah, ternak dibunuh, dibantai,” cetusnya.
Namun, klaim ini dibantah oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto, yang menyebut operasi gabungan TNI/Polri di Nduga adalah selain untuk pengamanan proyek Trans Papua yang melintasi Kabupaten Nduga, juga melakukan pengejaran untuk mencari pelaku serangan Desember silam.
Kesulitan yang dihadapi, karena banyak dari kelompok pro-kelompok Papua ini membaur dengan warga.
“Ketika mereka menyerang, mereka selalu berbaur dengan masyarakat. Wajar kalau masyarakat daripada menjadi korban, mereka mengungsi,” jelas Eko.
Namun, dia menegaskan, tidak semua warga Nduga pengungsi. Eko mengklaim ada warga Nduga yang “merasa aman dengan kedatangan pasukan kita.”
“Tetapi di satu sisi mereka merasa ketakukan karena OPM membaur, ada sisi intimidasi juga. Kita kesulitan membedakan OPM ketika sudah tidak bersenjata,” tutur Eko.
Terimpit di Tengah Konflik
Theo Hesegem menjelaskan beberapa pengungsi mengalami banyak penolakan, ketika tinggal di pengungsian.
Dia mencontohkan, anak-anak yang mengungsi di Walesi disuruh membayar oleh orang yang memiliki lahan ketika kedapatan menangkap ikan. Pengungsi lain, ketika sedang mencari kayu bakar, ditegur oleh warga setempat.
“Ini menunjukkan bahwa mereka tidak aman, di sana operasi [militer] kemudian di sini mereka tinggal, tapi tidak aman.”
Belum lagi, banyak yang pengungsi yang merasa trauma dengan kehadiran militer. Itu sebabnya, beberapa dari mereka menolak pemberian bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, karena dianggap penyaluran bantuan itu melibatkan militer.
Hal ini, menurut Theo, tak lepas dari trauma pengungsi atas keberadaan militer yang melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.
Selain itu, kepercayaan adat mereka bahwa mereka tidak bisa menerima bantuan dari “pihak musuh”.
“Budaya orang di sini kalau baku perang dengan musuh itu kita tidak bisa ambil, secara adat itu susah. Nanti mereka akan sakit dan mati semua.”
Namun, keterlibatan militer dalam pendistibusian bantuan, ditepis oleh Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Chandra Dianto.
Dia menyebut, pengerahan militer di Nduga adalah untuk pengamanan pembangunan proyek jalan Trans Papua dari gangguan kelompok bersenjata.
“Tentunya, terjadi eskalasi atau terjadi kontak tembak itu adalah salah satu tugas dalam rangka mengamankan pekerja.”
“Terjadinya kontak tembak itu karena munculnya gangguan-gangguan. Sehingga untuk mengurangi bantuan, mau tidak mau tugas TNI adalah untuk mengamankan, sehingga kontak tembak tidak bisa dihindarkan,” tutur Chandra.
Imbauan bagi Gereja-gereja Membangun Solidaritas
Konflik di Nduga, menurut tokoh HAM Papua yang juga imam Katolik Pastor John Djonga, tak lepas dari trauma masa lalu yang terjadi sejak tahun 1960an, saat sekelompok orang menghendaki kemerdekaan Papua dari NKRI.
Sejak itu, warga Nduga hidup di bawah pengalaman kekerasan militer, hingga saat ini. “Oleh karena itu menurut saya sekarang sudah tidak waktu lagi pihak Pemerintah Indonesia merasa mereka yang paling benar, OPM juga merasa mereka yang paling benar, karena berjuang untuk Papua merdeka. Tapi Papua merdeka dengan kematian sebanyak ini bagaimana itu?” ujarnya, seperti dilaporkan BBC News Indonesia.
“Saya berpikir sebagai orang gereja bagaimana kedua pihak ini harus berunding agar tidak ada lagi korban-korban,” kata Pastor John.
Menilik sejarah masa lalu orang Nduga dan konflik yang terjadi di wilayah yang menjadi pemekaran Kabupaten Jayawijaya itu, dia memandang pemerintah maupun pemimpin militer belum memahami masalah Nduga.
“Mereka hidup dibawah pengalaman-pengalaman kekerasan militer, operasi militer, sampai saat ini.”
“Karena itu sebenarnya bagaimana orang Nduga ini bisa hidup aman. Hidup aman menurut mereka tidak bisa aman dengan militer, tidak bisa dan sampai saat ini memang masih terjadi baku perang.”
Pdt Albertus Patty, Ketua Majelis Pekerja Harian Persekutuan gereja-gereja di Indonesia (MPH PGI) periode 2014-2019, mengatakan kepada Satuharapan.com, apa yang menimpa masyarakat di Nduga adalah ekspresi dari krisis kebangsaan dan krisis kemanusiaan. “Dalam krisis Nduga ini kita mengalami ironi yang menyedihkan karena di era kemerdekaan ini ada ribuan anak bangsa yang belum mengalami keamanan dan kenyamanan hidup, sehingga terpaksa lari ketakutan ke hutan-hutan dan menjadi pengungsi di tanah kelahiran sendiri,” katanya.
Negara telah gagal menghadirkan diri sebagai pelindung bagi warganya sendiri. “Saya berharap pemerintah segera menyelesaikan segala persoalan yang ada tanpa menimbulkan ketakutan dan menambah penderitaan bagi rakyat Nduga. Hentikan kekerasan. Jangan ada satu pun rakyat Nduga yang dikorbankan,” Pdt Patty menyerukan.
Pemerintah harus bisa menyelesaikan segala persoalan di Nduga dan di tanah Papua melalui dialog setara dan beradab, demi tercapainya keadilan bagi semua.
“Saya juga mengimbau gereja-gereja, dan tentu saja semua umat beragama, segera membangun kerja sama dan solidaritas untuk mengatasi situasi krisis yang dihadapi para pengungsi Nduga, dengan segera membantu mereka,” katanya.
Terlambat betindak, hanya memperparah krisis yang ada, katanya. “Para pengungsi adalah warga gereja dan warga bangsa ini. Bersikap diam terhadap penderitaan para pengungsi Nduga menunjukkan kelumpuhan spiritualitas dan menunjukkan krisis solidaritas kebangsaan,” ia mengingatkan.
“Inilah momen bagi gereja-gereja untuk berperan sebagai pelopor keadilan dan perdamaian, serta pelopor kebangsaan dan kemanusiaan,” katanya.
Kementerian Sosial mencatat setidaknya ada 2.000 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Wamena, Lanijaya, dan Asmat. Di antara pengungsi ini, tercatat 53 orang dilaporkan meninggal. Angka ini jauh di bawah data yang dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga, yang mencatat sedikitnya 5.000 warga Nduga kini mengungsi dan 139 di antara mereka meninggal dunia.
Data relawan menyebut pengungsi di Wamena tersebar di sekitar 40 titik. Kebanyakan dari mereka tinggal menumpang di rumah kerabat.
Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, di dalam satu rumah atau honai bisa berisi antara 30-50 orang. (bbc.com/satuharapan.com)
Editor : Sotyati

Tembakan Pertahanan Udara di Isfahan, Iran, Belum Jelas seba...
TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Serangan pesawat tak berawak Israel terhadap Iran menyebabkan pasukan Iran ...