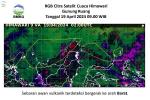Minoritas Sekeras Baja
Selama ini kaum minoritas kerap mengidap Cinderella Complex: selalu minta diurus dan diperhatikan kelompok mayoritas. Dan sikap ini dapat meninabobokan mereka. Padahal sejarah berjalan saat minoritas berani melawan demi perubahan.

SATUHARAPAN.COM - Pertandingan babak penyisihan Grup A Piala Eropa 2016 antara tuan rumah Perancis dan Albania pada 16 Juni 2016 meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Sebelum menonton pertandingan ini, publik menganggap tim debutan Albania pasti menjadi “ayam opor” bagi Perancis yang merupakan salah satu raksasa sepakbola Eropa.
Jangan hanya terpana pada hasil akhir, perlawanan Albania menahan raksasa Perancis hingga hampir imbang adalah usaha sangat jantan. Pemain Albania tidak menjadi minoritas menderita di depan Goliath Francia. Mereka bekerja keras di tengah “ketidak-seimbangan” wasit (dalam beberapa episode menguntungkan tuan rumah) dan mayoritas penonton yang terus mengintimidasi. Mereka memanjat asa hingga titik darah penghabisan; tidak memainkan sepak bola negatif dengan man to man marking, tapi tetap menjaga wilayah (zone marking) secara kreatif mencari peluang serangan balik.
Tulisan ini hampir sempurna jika hasilnya tidak seperti yang sudah kita ketahui. Selama 89 menit mereka berduel tanpa grogi melawan Perancis. Para “artis” Perancis seperti Oliver Giroud, Paul Pogba, dan Anthony Martial gagal menceploskan bola ke gawang mereka. Yang menggolkan malah Antoine Griezmann, pemain pengganti dari “minoritas Madrid”(Atletico Madrid). Kalau pun Dimitri Payet bisa menjebol gawang di injury time, itu karena pemain Albania sudah tidak memperhatikan lagi pertahanan. Ingat, Payet pun bukan anak emas awalnya di skuad Perancis.
Tangguh di Tengah Kepungan
Semangat spartan itu tidak muncul tiba-tiba. Meskipun Albania hanya sebuah “noktah” di Eropa, sejarah mereka telah dikenal sejak lebih 2000 tahun lalu. Imperium besar dunia pernah mengolonialisasi mereka: mulai Kekaisaran Romawi, Byzantium, Khilafah Usmaniyah, Italia, dan Jerman, tapi mereka tidak pernah takluk.
Mereka kerap menganggu iring-iringan kerajaan dan merampok kembali pajak dari daerah jajahan yang dipungut. Oleh sejarah pemenang mereka dianggap bandit (Hajduk), tapi oleh masyarakat Albania mereka adalah pahlawan (Richard W. Slatta, Bandits and Social Rural History, 1991). Dibandingkan Perancis yang serba mengilap sejarah dan kontinennya (luas 640.679 km2 dan penduduk 67 juta), Albania sungguh minoritas dalam angka (luas 28.748 km2 dan penduduk 2,8 juta).
Demikian juga secara agama, meskipun penduduk Albania 60 persen muslim, masyarakatnya sangat sekuler bahkan cenderung ateistik. Mereka tidak tunduk pada simbolisme Turki karena kehadiran Dinasti Ustmaniyah dalam sejarah Albania penuh tragedi. Mereka tetap mengagungkan identitas Albania dibandingkan identitas agama dan kultur impor.
Gabungan antara minoritas dan kultur puritan Albania menyebabkan mereka kerap distigmaisasi macam-macam. Seperti terlihat di film Taken (2008), kaum Tropoja Albania digambarkan sebagai mafia sadis. Film Hollywood itu gagal berempati atas sejarah Albania dan cenderung mensimplifikasi. Padahal kultur kekerabatan mereka sangat komunalistik, setia kawan, dan cinta keluarga.
Sikap “minoritas melawan” juga terlihat pada kasus kerusuhan Singkil 13 Oktober 2015. Ada satu gereja di Dusun Danguran Desa Kutakerangan yang awalnya akan dibakar massa, tapi tidak jadi karena masyarakatnya mempertahankan dengan tenaga dan senjata. Tragedi penembakan Singkil terjadi di daerah Danguran itu. Gereja Danguran awalnya masuk rencana bongkar tapi gagal karena kerasnya prinsip warga mempertahankan rumah ibadah mereka.
Dari wawancara saya dengan komunitas muslim Singkil menyebut masyarakat Danguran memang aneh. Mereka dianggap memiliki sub-kultur sendiri dan solidaritas unik. Bagi muslim Singkil, Danguran tidak merepresentasikan karakter Singkil.
Namun ketika saya mewawancarai komunitas Kristen, mereka lihat sebaliknya. Seorang warga Desa Situbuh-tubuh Kecamatan Danau Paris melihat masyarakat Danguran sederhana dan toleran. Mereka kerap membantu keluarga muslim sekitar yang memiliki hajatan. Masyarakat Danguran digambarkan terbuka, berbeda dengan pandangan sebelumnya yang melihat mereka serba introvert.
Melawan untuk Perubahan
Gambaran dua kasus itu menunjukkan bahwa situasi minoritas tak harus diratapi dan didramatisasi. Dalam situasi apapun minoritas-mayoritas pasti terbentuk, karena secara populasi pasti ada yang lebih inferior. Demikian pula kelompok superior (secara numerik) pasti menggunakan pelbagai pendekatan (baik sadar atau tidak) untuk mengidentifikasi diri berbeda dengan kelompok minoritas. Itu sunnatullah, conditio sine qua non, realitas empiris duniawi.
Strategi yang kerap diambil untuk menangani problem minoritas selama ini masih konvensional: membangun empatik semata atas situasi ke-minoritas-an sebuah komunitas dan memproteksi sedemikian rupa, tapi lupa membangunkan sisi objektif mereka untuk berubah. Padahal penting sekali dilakukan bagi kaum lemah, seperti dikatakan Tania Murray Li, antropolog Toronto University, menemukan hasrat untuk berkembang (the will to improve).
Sikap terlalu memanjakan atau menganggap lemah minoritas akan berpengaruh kepada kematangan kaum minoritas dalam memikirkan nasibnya. Mereka harus disadarkan untuk bergerak, “melawan”, dan menuntut hak daripada terus-menerus menerima iba dengan solusi karikatif.
Karena jika pilihannya hanya melanjutkan advokasi konvensional seperti selama ini dijalankan, akan menjerambabkan minoritas kepada kultur – seperti diistilahkan Colette Dowling: Cinderella Complex, yaitu ketika hasrat tak sadar (unconscious desire) sekelompok masyarakat minoritas untuk dipedulikan dan diurus oleh orang lain. Cinderella complex ini adalah gangguan perkembangan psiko(sosial) sehingga tidak kunjung matang, mandiri, dan bertanggung-jawab.
Padahal sejarah sudah menunjukkan diktat perubahan melalui seorang minoritas. Namanya Muhammad Ali (Cassius Clay). Ali bukan sekedar seorang juara legendaris kelas berat dunia tiga kali, tapi juga seorang jenius dan aktivis. Pada tahun 1964, di tengah melambung namanya di dunia tinju, ia memilih masuk Islam. Islam dan kulit hitam adalah subaltern minoritas di AS yang Kaukasia dan Kristen. Namun masuknya Muhammad Ali ke agama Islam membawa kegairahan baru bagi kaum Afro-Amerika menuntut persamaan hak lebih luas.
Kehadirannya bukan saja mengubah pandangan AS tentang Islam dan kulit hitam tapi juga membawa pengaruh ke dunia Islam dalam melihat negeri Paman Sam. Ia pernah menolak wajib militer karena menganggap tak cukup alasan memerangi bangsa di luar AS yang tidak memiliki dosa terhadap keluarga dan kaumnya. Ia mengutuk sikap brutal tentara AS di Vietnam. Di sisi lain, ia pernah mogok keluar dari Irak hingga Presiden Saddam Hussein melepaskan sandara sipil AS. Barrack Obama menyebut Muhammad Ali sebagai inspirator “kurang ajar”. Ia menguji kebebasan fundamental Amerika dalam berekspresi, beragama, dan memiliki semangat perubahan yang benar.
Ali menunjukkan bahwa menjadi minoritas tidak harus inferior. Kaum minoritas harus didesak menunjukkan keinginan dan harapannya melalui kerja keras dan perlawanan. Mereka tidak perlu mulut bergincu untuk merepresentasikan keinginannya dari orang lain yang malah bisa salah baca (misreading).
Di dunia Islam, Syiah adalah minoritas. Populasinya hanya 12 persen dari total umat Islam. Namun AS, Israel, dan sekutu Blok Barat lebih takut kepada Iran, Suriah, Lebanon, Hezbollah, dan intelektual Syiah yang brilian. Terbukti minoritas yang kreatif dan pemberani lebih mulia posisinya, karena bisa membentengi diri untuk tak bersikap naif, berkeinginan sekeras baja, dan tak takut kalah. Mereka akan tercatat di dalam transkrip publik dan sejarah dunia dibandingkan minoritas yang pasif dan pasrah saja.
Penulis adalah Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
Editor : Trisno S Sutanto

Israel Mengatakan Akan Membalas Iran, Inilah Risiko-risiko Y...
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Israel bersumpah untuk membalas Iran, berisiko memperluas perang bayangan...