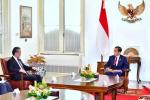Potret Pendukung Papua Merdeka di Kamp Pengungsi Australia
MANUS, PAPUA NUGINI, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Papua Nugini mengatakan sekitar 10.000 orang Papua kini berada di negara itu dan menunggu giliran untuk disahkan menjadi warga negara. Bulan lalu, 300 orang rombongan pertama sudah memperoleh kewarganegaraan.
Orang-orang itu yang sebagian di antaranya adalah pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melarikan diri dari Indonesia, tersebar di berbagai tempat di PNG. Sebagian dari mereka kini masih bertahan di eks kamp pengungsi Australia, di kepulauan Manus.
Sebuah laporan investigasi yang ditulis oleh Stefan Armbruster pada sbs.com.au, menceritakan bahwa kamp pengungsi yang dijuluki juga sebagai Kamp Salasia ini didirikan hampir 50 tahun lalu, ketika Papua Nugini masih menjadi wilayah jajahan Australia. Letaknya hanya beberapa ratus meter dari pusat penahanan imigrasi Australia, di Manus, yang dalam waktu dekat akan ditutup. Tempat ini sempat heboh karena menjadi topik pertengkaran antara PM Australia, Malcolm Turnbull dan Presiden AS, Donald Trump.
Para simpatisan Papua Merdeka telah berada Kamp Salasia sejak setengah abad lalu, sejak kamp itu didirikan. Mereka menjalani kehidupan dan membentuk keluarga, beranak-pinak melalui pernikahan dengan penduduk setempat.
Dulunya, kamp pengungsi di Manus dibangun untuk menghindari konfrontasi diplomatik dengan Indonesia. Di kamp ini Australia mengisolasi sejumlah kecil tokoh Papua yang beraspirasi untuk merdeka, yang melarikan diri dari Indonesia.
Melarikan diri dari Indonesia
Operasi militer Indonesia atas Papua pada tahun 1960-an, memicu krisis pengungsi. Ribuan 'pelintas batas' melarikan diri ke Papua Nugini yang saat itu masih menjadi koloni Australia.
"Kami datang sebagai pengungsi ke pulau Manus. Pemerintah (Belanda) memindahkan kami," kata Manfred Meho, yang tiba di Manus saat berusia tiga bulan dengan sebuah pesawat Caribou Australia dari kamp-kamp di dekat perbatasan dengan Indonesia.
"Ada krisis politik, pertempuran di Papua antara OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan tentara Indonesia. Orang tua kami, saat mereka melarikan diri, adalah pendukung Papua (Merdeka)," kata dia.
Banyak di antara pelintas batas itu berhasil diusir oleh petugas patroli Australia, yang disebut kiaps, di perbatasan. Namun tidak sedikit yang akhirnya mendapatkan visa "permissive residence." Rombongan pertama dari mereka dikirim ke Manus pada tahun 1968.
Sejumlah penduduk asli Papua dan keturunan mereka masih tinggal di kamp ini, menikah dengan masyarakat setempat, membesarkan anak-anak mereka dan bahkan ikut dalam pemilu di PNG.
Seperti ribuan orang Papua yang telah datang ke PNG sejak itu, mereka hidup tanpa kewarganegaraan sampai sekarang. Hal ini secara resmi diakui oleh pemerintah Papua Nugini.
"Kami memiliki sejumlah besar pengungsi 'Irian Barat' di Papua Nugini," kata PM Papua Nugini, Peter O'Neill, kepada SBS World News, belum lama ini.
"Sebenarnya banyak di antara mereka, yang mendekati 10.000 orang, tergolong memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Papua Nugini. Beberapa minggu yang lalu 300 orang pertama sudah berpartisipasi dalam sebuah upacara yang menempatkan mereka di negara ini," kata O'Neill.
Mereka Tidak Dikehendaki
Pada tahun 1960-an Australia tidak menghendaki kedatangan orang Papua itu. Namun karena jumlah mereka yang banyak dan medan terpencil yang sulit di PNG, Australia tidak dapat memulangkan mereka semua.
"(Australia) menganggap mereka sebagai gangguan, karena berpotensi menyebabkan masalah hubungan dengan Indonesia," kata profesor sejarah Klaus Neumann, dari Deakin University.
"Australia tidak keberatan dengan pengambilalihan Indonesia atas Papua sebagai eks jajahan Belanda, dan Australia telah mengakui bahwa Indonesia bertanggung jawab atas Papua (Barat), jadi akan menjadi masalah diplomatik bagi Australia jika mereka memberikan status pengungsi," kata dia.
Namun, pada tahun 1964, Australia mulai mengeluarkan visa ke sejumlah kecil 'pelintas batas.'
"Ini adalah orang-orang yang mampu membuktikan bahwa mereka dianiaya di Papua. Namun Australia sangat berhati-hati untuk mengatakan bahwa mereka bukan pengungsi. Mereka tidak ingin melibatkan UNHCR (badan pengungsi PBB), mereka ingin (UNHCR) keluar dari wilayah tersebut, " kata Profesor Neumann.
Ia menambahkan ada dua alasan utama mengapa Australia tidak tertarik pada mereka (orang Papua) yang tinggal di perbatasan. Pertama, Australia tidak ingin OPM menggunakan wilayah Australia dan menggunakan kamp sebagai tempat berlindung setelah pertempuran dengan pihak Indonesia.
Kedua, Australia tidak ingin beberapa pemimpin Papua Merdeka melakukan propaganda anti-Indonesia. Mereka tidak menginginkan terlibat dalam kegiatan anti-Indonesia, dan mempermalukan Indonesia, atau meminta orang Papua Nugini atau orang asing lainnya bergabung dalam demonstrasi untuk memprotes kehadiran Indonesia di Papua.
"Jadi mereka (pihak berwenang Australia) berpikir dengan mengirim mereka ke tempat yang paling terpencil di PNG akan menghindarkan mereka dari aktivitas anti-Indonesia," kata Neumann.
Selain itu untuk wartawan, Manus jauh lebih sulit untuk diakses dari PNG daratan.
Beberapa tokoh Papua Merdeka yang mengungsi ke Australia mencoba untuk mendapat perhatian internasional.
Clemens Runawery dan Willem Zonggonau, (keduanya sudah meninggal), misalnya, pernah mencoba pergi ke markas PBB pada tahun 1969.
"Wim dan saya meninggalkan Papua untuk terbang ke New York menginformasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) itu korup," kata Runawery dalam sebuah iklan televisi Australia pada tahun 2007.
Apa daya mereka tidak berhasil. "Kami dipaksa turun dari pesawat oleh pejabat Australia, di bawah tekanan rezim militer Indonesia. Kami tidak pernah bisa menceritakan fakta sebenarnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Runawery.
Mereka kemudian dikirim ke Manus, bersama puluhan pengungsi lainnya.
Di mata pemerintah Australia, keberadaan Manus sangat membantu dalam menjaga keamanan negara. Itu terlihat dari sebuah surat internal tentang hal ini di lingkungan Kemenlu Australia.
"Sebagai pusat penahanan yang terletak jauh dari perbatasan dan dimana komunikasi dengan Papua cukup sulit, Salasia Camp, melayani tujuannya dengan baik," demikian kepala Departemen Luar Wilayah Australia, menulis kepada mitranya di Kemenlu negara itu pada bulan Februari 1972.
Hal ini yang membuat Australia tidak merekomendasikan kamp dibuat di Papua Nugini daratan. Apalagi di Manus diharapkan mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik.
"Perlu dipertimbangkan ulang bahwa Kamp Manus harus dipertahankan seperti sekarang, dan tuduhan tentang kondisi di dalam, dan kesehatan penghuni, sama sekali tanpa dasar," demikian laporan yang ditujukan kepada Kemenlu Australia.
Protes Michael Somare
Pada tahun 1968, Michael Somare, yang kemudian menjadi perdana menteri pertama Papua Nugini, mengangkat isu 'pelintas batas' di parlemen prakemerdekaan Papua Nugini. Ia mengatakan mendengar kabar bahwa pengungsi di Manus ditempatkan di kamp dekat kantor polisi.
"Ini bisa dibandingkan dengan Perang Dunia Kedua ketika orang-orang Yahudi ditempatkan di kamp konsentrasi," katanya.
Dia menambahkan bahwa Papua Nugini adalah "negara bebas" dan para pengungsi harus diperlakukan secara adil dan mereka harus mendapatkan pekerjaan.
Pada bulan Mei 1969, wartawan Jack McCarthy pergi ke Manus untuk membuat reportase tentang keadaan kamp pengungsi itu dan diterbitkan di South Pacific Post. Ia menuliskan laporannya dengan judul 'Tahanan Pengungsi Hidup Tanpa Harapan' dan menggambarkan di sana pengungsi dalam kondisi yang menyedihkan.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Australia mengirim seorang pejabat untuk menyelidiki. Berbeda dengan laporan McCarthy, pejabat itu melaporkan bahwa kamp tersebut dalam kondisi baik walaupun tingkat pengangguran meluas.
Menurut pejabat tersebut, Salasia Camp "tidak sesuai" dan Manus "terlalu kecil" bagi para pengungsi untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu direkomendasikan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dan sebagai imbalannya, para pengungsi berkewajiban melakukan pekerjaan-pekerjaan umum, termasuk pekerjaan kasar.
Selain itu, laporan pejabat itu juga mengungkapkan kemungkinan para pengungsi dikembalikan ke Papua asalkan beberapa syarat terpenuhi.
"Jika, dan ini yang utama, ada penerimaan dari orang-orang yang tinggal di Papua hasil referendum (terhadap kehadiran kembali simpatisan Papua Merdeka), dengan relaksasi dan perubahan yang diperlukan dalam kebijakan pemerintah Indonesia, dan para pengungsi ini tidak melihat ada masa depan yang cerah di Papua Nugini, mereka mungkin akan mengambil kesempatan untuk pulang," kata laporan pejabat tersebut.
Papua Tak Memberi Harapan
Menurut catatan, pada bulan Februari 1972 tersisa 73 orang di kamp tersebut. Sebanyak "43 laki-laki dewasa dengan tanggungan 69 orang dan satu perempuan dewasa (janda) dengan satu anak" telah diproses, sebuah laporan dari Departemen Luar Wilayah pada tahun 1972 menyatakan.
Dari keseluruhan mereka, tiga di antaranya telah kembali ke Papua "atas kemauan mereka sendiri", satu orang pergi ke Belanda dan 39 orang dan tanggungan mereka "menemukan pekerjaan dan telah menetap di berbagai pusat pengungsian di seluruh Papua Nugini".
"Awalnya diperkirakan (Manus) ini akan menjadi tempat penampungan sementara sampai permintaan izin permisif mereka diputuskan," kata profesor Neumann.
Namun, "beberapa di antara pengungsi itu tinggal lebih lama lagi." Akibatnya, Kamp Manus pun menjadi permanen.
"Kamp penampungan pengungsi ini bukan tempat penahanan, tidak ada pagar kawat berduri di sekelilingnya dan orang dapat datang dan pergi menurut keinginan mereka," kata Neumann.
"Pada kenyatannya, pihak pemerintah menginginkan mereka mencari pekerjaan dan pemerintah agak kecewa karena mereka tidak mau, pemerintah juga ingin anak-anak mereka sekolah. Jadi tempat ini sama sekali tidak seperti sebuah pusat penahanan," terang Neumann.
Manfred Meho menghabiskan seluruh hidupnya di kamp itu. Ia pernah mencoba kembali ke Papua tetapi hanya sebentar.
"Ini adalah kehidupan yang baik. Penduduk Manus juga baik. Semua rumah di sini dibangun oleh pemerintah sejak pertama kali kami ke sini," kata dia.
Australia membelanjakan US$ 15.000 untuk pembangunan 12 rumah di kamp ini. Keadaan sangat baik itu sempat mereka alami, sebelum pada tahun 1975-76 pemerintah menghentikan pasokan makanan.
Banyak di antara para pengungsi yang asli kini telah meninggal atau pindah ke tempat lain di Papua Nugini. Beberapa di antara mereka kembali pe Papua.
Pada tahun 2005 ada pembicaraan antara Papua Nugini dan Indonesia. Dubes Indonesia untuk Papua Nugini kembali menawarkan repatriasi sukarela bagi orang Papua di Papua Nugini.
Salah seorang yang sempat pulang ke Papua adalah Amos Kimbri. Orang tuanya datang ke kamp ini pada pertengahan 1970. Ayahnya tinggal di Papua Nugini tetapi ibunya kembali ke Papua.
Pada 2010 Amos kembali ke Papua. Tetapi hanya sebentar. Ia kemudian pulang lagi ke Manus. Menurut dia, hidup di Papua terlalu keras.
"Di sini kami bebas, tidak ada persoalan. Tetapi di Papua, banyak persoalan," kata dia. Ia menyebut sulitnya mendapatkan lahan dan bercocok tanam serta tiadanya sekolah untuk anak-anak.
"Saya berada di sana ketika mereka menembaki rakyat Papua. Mereka berkata kami tak boleh memiliki bendera Papua, ketika kami menyimpannya, mereka akan membunuh kami, karena itu saya dan istri serta putra-putri saya kembali ke Papua Nugini," kata dia.
Sekarang Amos menjadi warga yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Ia tinggal di Papua Nugini tetapi ia bukan warga negara Papua Nugini. Ia memiliki paspor sehingga ia dapat bepergian hingga ke Singapura, Filipina dan Vietnam. Tetapi ia tidak memiliki kewarganegaraan.
Kini pemerintah Papua Nugini menawarkan kewarganegaraan kepada mereka. Bagi Manfred Meho, kembali ke Papua yang merdeka hanyalah sebuah mimpi yang jauh. Dan ia sudah terlanjur mencintai Manus.
"Orang-orang di sini tidak bahagia ketika mereka memikirkan Papua dan merasa sedih, tetapi hidup di sini enak," kata dia.
"Rakyat Manus adalah orang-orang baik. Kami pergi memancing bersama, berkebun, mengambil sagu dan mereka bersahabat dengan kami."
Editor : Eben E. Siadari

Tembakan Pertahanan Udara di Isfahan, Iran, Belum Jelas seba...
TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Serangan pesawat tak berawak Israel terhadap Iran menyebabkan pasukan Iran ...