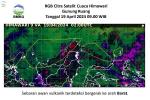Teror di Paris: Mengapa?
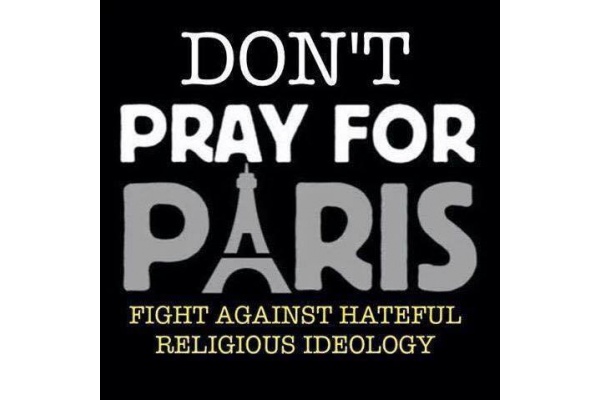
Paris, Satuharapan.com – Berita mengejutkan itu datang Jum’at (13/11) malam. Di pusat kota Paris lagi-lagi berlangsung serangan teroris yang sistematis pada lima titik dan menimbulkan korban jiwa sangat besar. Sampai Sabtu (14/11) siang, dilaporkan setidaknya 153 orang meninggal akibat penembakan sadis – korban paling banyak di dalam gedung konser Bataclan, yang sedang menggelar konser band asal Kanada – dan bom bunuh diri di depan Stade de France, serta sekitar 200 orang luka-luka.
Dunia pun terguncang. Dalam sekejap, para pemimpin dunia mengutuk kebiadaban kaum teroris itu. Tetapi reaksi dunia juga terpecah. Sebagian pendukung negara teroris ISIS malah merayakan peristiwa itu lewat media sosial, dengan tagar mencolok: #ParisIsBurning. Sebagian lain mewanti-wanti agar terorisme jangan dikaitkan dengan isu imigran yang kini membanjiri Eropa. Seperti dicuitkan Dan Holloway (@RFCdan) dalam akun Twitter-nya, justru para imigran itu melarikan dari negara mereka karena kekerasan ISIS yang mereka alami di negara sendiri.
Wanti-wanti juga segera muncul untuk tidak mengaitkan serangan Jum’at malam itu dengan Islam. Hal itu muncul karena salah satu saksi mata peristiwa penembakan di gedung konser menuturkan, para teroris itu menembak sembari meneriakkan, “Allah Akbar!” Tetapi kesaksian itu dibantah Julian Pearce, jurnalis Europe 1, yang juga berada dalam gedung. Seperti dituturkan The Guardian, Pearce mengaku tidak mendengar teriakan itu.
Memang sulit sekali memastikan soal teriakan tersebut di tengah keributan yang terjadi. Marc Coupris, kepada The Guardian, melukiskannya bak pembantaian di medan perang. “Seperti di medan perang, banyak darah di mana-mana, juga tubuh di mana-mana,” katanya. “Semua orang tiarap. Saya telungkup di lantai ditindih seorang lelaki, dan orang lain di samping saya menempel ke dinding. Kami seperti itu entah berapa lama. Rasanya seperti selamanya.”
Terlepas dari soal siapa yang benar dalam kesaksian itu, orang segera menghubungkan serangan teror di Jum’at malam dengan penyerangan ke kantor mingguan Charlie Hebdo, hampir setahun lalu. Apalagi empat lokasi serangan selain Stade de France yang terletak di St. Denis, sebelah utara Paris, memang dekat dengan lokasi kantor mingguan tersebut.
Mungkin ada baiknya kita melihat kaitan ini lebih jauh.
Prancis yang Berubah?
Masih ingat serangan ke kantor mingguan Charlie Hebdo? Pada Rabu (7/1/2015) siang hari, dua orang kakak beradik, Saïd dan Chérif Kouachi, menerobos kantor mingguan Charlie Hebdo di pusat kota Paris, dan menembak mati 11 orang serta melukai 11 orang lain di dalam kantor. Ketika keluar, mereka menembak mati seorang polisi Prancis.
Dunia terkejut dengan peristiwa itu. Simpati pun datang dari seluruh pelosok jagat, dan membuat tagar #JeSuisCharlie menjadi trending topic di jagat maya. Hari Minggu (11/1/2015), empat hari kemudian setelah peristiwa tersebut, berlangsung demonstrasi damai yang terbesar di Prancis. Sekitar 2 juta orang, termasuk lebih dari 40 kepala negara, menghadiri demonstrasi demi persatuan nasional di Paris, serta 3,7 juta orang melakukannya di seluruh Prancis. Charlie Hebdo tetap terbit, dan tirasnya melonjak jadi 7,95 juta eksemplar dalam enam bahasa (dibanding 60.000 eksemplar biasanya dalam bahasa Prancis). Paling tidak itu menurut Wikipedia.
Namun bukan soal penembakan, maupun reaksi dunia terhadap penembakan itu, yang membuat tragedi Charlie Hebdo perlu direnungkan. Ada soal yang jauh lebih mendasar. Seperti diingatkan Mark Lilla, kolumnis The New York Review of Books tak lama setelah tragedi itu terjadi, serangan ke Charlie Hebdo hanyalah puncak gunung es dari proses perubahan di dalam masyarakat Prancis, terutama di kalangan anak-anak muda.
Anak-anak muda itu bisa datang dari mana saja, imigran atau penduduk Paris; bisa beragama apa saja, entah Muslim, Kristen, atau bahkan ateis. Namun rata-rata mereka datang dari keluarga yang berantakan, lalu tertarik dengan ide-ide kelompok jihadis ekstrem ala ISIS, terutama lewat chatting, Skype, Twitter, dll. Sementara para perempuannya tersentuh oleh rasa “kemanusiaan”, sehingga bergabung demi bantuan kemanusiaan. Lilla menyebut cerita-cerita mereka yang dikumpulkan Dounia Bouzar, Ils cherchent le paradis ils ont trouvé l’enfer (Mereka mencari Surga, tetapi menemukan Neraka). Bouzar sendiri seorang antropolog, dan mendirikan semacam pusat rehabilitasi guna mencegah anak-anak muda ini pergi berjihad ke Suriah atau Irak.
Perang Ideologis
Tuturan Lilla itu memperlihatkan, serangan terhadap Charlie Hebdo maupun teror Jum’at malam lalu di Paris bukan hanya persoalan terorisme biasa (yang biasa dihadapi oleh aparat keamanan), tetapi menyangkut persoalan yang lebih besar: suatu “krisis makna”, memakai istilah Paul Brandeis Raushenbush, dalam tulisannya yang sangat menarik mengenai ISIS di Huffington Post.
Dalam tulisannya itu, Raushenbush mengutip penelitian Ed Hussain, anggota senior CFR (Council on Foreign Relations) yang mengejutkan: ideologi jihadis radikal ala ISIS ternyata menarik pengikut paling banyak di kalangan anak muda, berusia 18 – 25 tahun, yang kesepian dan sedang mencari identitas serta sense of belonging. Ideologi jihadis radikal ala ISIS menarik mereka, karena seakan memberi tujuan yang lebih besar dan makna bagi kehidupan mereka, sekaligus memberi saluran bagi kemarahan terhadap ketidakadilan global yang diakibatkan oleh “Kapitalisme” atau “Dominasi Barat”.
Itu sebabnya, Husain mengingatkan bahwa perang terhadap ISIS bukan hanya perang senjata, tetapi juga perang ideologis. “Dengan kata lain, sementara taktik militer mungkin efektif untuk jangka pendek, tetapi kamu tidak bisa membom ideologi,” tulis Raushenbush. “Kau harus melawannya dengan ideologi yang lebih baik.”
Persis di situlah persoalan yang sekarang harus dihadapi Presiden Hollande. Jika benar, seperti dikutip The Guardian dari sumber-sumber resmi, bahwa diperkirakan ada 520 warga negara itu yang kini berperang di Suriah untuk ISIS dan separonya “pulang” ke tanah air, maka wanti-wanti Lilla dan Raushenbush sungguh penting diperhatikan.
Mari kita tunggu langkah-langkahnya!
Penulis adalah Koordinator Penelitian Biro Litbang-PGI, Jakarta
Editor : Trisno S Sutanto

Israel Mengatakan Akan Membalas Iran, Inilah Risiko-risiko Y...
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Israel bersumpah untuk membalas Iran, berisiko memperluas perang bayangan...