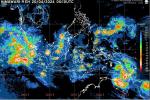Diskriminasi Ras vs Sumpah Pemuda

SATUHARAPAN.COM – Penentangan suatu ormas terhadap pelantikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dapat dimungkiri dilatarbelakangi isu ras dan agama (Tionghoa Kristen). Tampak ada upaya penggiringan opini bahwa minoritas etnis dan agama tidak berhak memimpin wilayah Indonesia. Tentu ini bertentangan dengan Sumpah Pemuda. Putra-putri Indonesia pendiri RI menyadari bahwa kemerdekaan dapat diraih dan diperjuangkan dengan Persatuan Indonesia. Kegagalan meraih kemerdekaan waktu itu karena kita tidak menyadari telah menjadi korban politik devide et impera. Spirit Sumpah Pemuda ialah bahwa semua suku/ras maupun agama di Indonesia adalah putra-putri Indonesia yang bertanah air satu, yang ikut memperjuangkan Indonesia dan tidak patut membeda-bedakan maupun dibeda-bedakan. Penjunjungan Bahasa Indonesia, yang dari etnis minoritas, menandaskan bahwa bangsa Indonesia melawan diskriminasi meski terhadap minoritas.
Kenapa etnis Tionghoa di masa lalu telah diragukan untuk dipercaya memimpin wilayah Indonesia? Benih-benih pembedaan rasial bagi pemimpin Indonesia masih tampak dalam ketentuan tentang syarat presiden RI dalam pasal 6 teks asli UUD ’45, yakni haruslah Indonesia asli. Namun hal utama yang perlu menjadi pertanyaan kita ialah: siapakah yang Indonesia asli itu? Para sejarawan pun tahu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia memiliki ras mongoloid, dan nenek moyang kita berasal dari seberang lautan, yakni dari kawasan Indochina. Karena itu ada lagu anak-anak: “Nenek Moyangku Orang Pelaut”. Maka sudahlah tepat apabila amendemen UUD merevisi syarat “Indonesia asli” itu menjadi “harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden”.
Umumnya negara demokrasi menentang oligarki (kekuasaan atas dasar kelompok orang) dan mengutamakan meritokrasi (kekuasaan berdasarkan kompetensi). Amerika Serikat, yang juga bineka seperti Indonesia, juga menganggap orang yang lahir di Amerika ialah orang Amerika. Mereka tidak memedulikan apakah matanya sipit, rambutnya hitam, atau bahkan kulitnya hitam. Itulah sebabnya Barack Obama dapat menjadi presiden meski dari ras minoritas. Filipina pun pernah memiliki presiden Fidel Ramos yang Kristen Protestan, meski 85% warga negara Filipina ialah Katolik.
Pada akhirnya yang menentukan nasionalisme seseorang ialah rekam jejaknya membela kepentingan nasional. Saat Penjajah Jepang mulai masuk Indonesia, kita sempat salah mengira bahwa mereka ialah saudara sebangsa yakni Asia Timur Raya. Namun ketika mereka bertindak tidak adil, bahkan menindas kita, maka kita sadar bahwa nasionalisme mereka tidak di pihak kita. Demikian pula yang menjadi tolok ukur perasaan rakyat Papua dan Aceh terhadap kebangsaan Indonesia ialah apakah kondisi adil dan makmur juga dinikmati mereka.
Masalah utama yang melatarbelakangi penolakan Ahok sebagai pemimpin DKI ialah identitasnya yang Tionghoa Kristen. Orang-orang Kristen Indonesia yang memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sudah banyak dikenal, seperti Wolter Monginsidi, Slamet Rijadi, Johannes Leimena, Pierre Tendean, Kol. R. Sugiyono, T.B. Simatupang, dll. Namun bagaimana dengan etnis Tionghoa? Apakah mereka juga terlibat dalam memperjuangkan Indonesia?
Sejarawan Prof. Dr. Slamet Muljono (1968) memaparkan bahwa para Wali/Sunan dan Sultan yang secara tak langsung membentuk Indonesia ternyata juga tak sedikit yang berdarah Tionghoa, seperti Sunan Ampel (Bong Swi Koo), Sunan Kalijaga atau Raden Said (Gan Si Cang), Sunan Gunung Jati (Toh A Bo), dan Sunan Kudus (Ja Tik Su), serta Sultan Demak pertama yakni Raden Patah (Jin Bun). Sekalipun tidak semua sepakat , namun setidaknya tak dapat dimungkiri bahwa terdapat banyak jejak arsitektur dan kuliner Tiongkok di daerah pesisir utara Jawa yang basis Muslimnya kuat.
Dalam zaman VOC, perjuangan melawan penjajah tak sedikit juga dilakukan oleh etnis Tionghoa, terutama dalam “Perang Kuning” dan khususnya di Lasem (sebagaimana yang ditulis Asvi Warman Adam dalam Tionghoa dalam Kanvas Raksasa serta dalam Kitab Carita Sejarah Lasem karya Raden Panji Kamzah yang ditulis ulang Raden Panji Karsono tahun 1920). Sejak abad ke-17, imigrasi warga Tionghoa ke Batavia cukup deras. Hubungan mereka dengan penduduk setempat berlangsung harmonis. Kemampuan mereka berdagang maupun berbaur dengan warga pribumi membuat VOC cemas. Mereka khawatir niatnya menguasai Nusantara tidak tercapai karena penduduk pribumi lebih bersimpati terhadap warga etnis Tionghoa dibandingkan kepada orang Belanda. Akhir tahun 1739 sampai Imlek 1740, VOC menangkap sekitar 100 orang Tionghoa dari Bekasi hingga Tanjung Priok. Warga Tionghoa pun segera menyusun strategi menghadapi VOC. Mencium gelagat itu, de Roy, kepala personalia setempat, melaporkan kepada Gubernur Adriaan Valckenier bahwa warga Tionghoa sedang menghimpun kekuatan. Maka Valckenier memberlakukan resolusi penangkapan kepada warga Tionghoa yang dianggap mencurigakan. Pembantaian yang dimulai 9 Oktober 1740 pada awalnya menahan dan membantai 500 orang Tionghoa, kemudian meluas ke rumah sakit dan seluruh kota, hingga memakan korban jiwa lebih dari 10.000 jiwa. Karena tahun 1740 kota Batavia dihancurkan dan banyak orang Tionghoa dibantai, banyak pula orang Tionghoa melarikan diri ke Tangerang dan berbenteng di sana. Mereka menetap dan mengolah tanah di situ, mereka pun menjadi “pribumi” di situ, dikenal sebagai “Cina Benteng”. Sampai saat ini pun banyak “Cina Benteng” yang miskin, bahkan ikut tergusur oleh pembangunan Bandara Soekarno-Hatta.
Sementara itu karena Batavia dimusnahkan, kurang lebih 1.000 orang Tionghoa Batavia juga lari mengungsi ke Lasem, mengingat adipatinya, Mayor Oei Ing Kiat, adalah orang Tionghoa Muslim yang bersahabat dengan bangsawan Jawa, dan bersikap mengayomi. Akibat kerusuhan di kota-kota di Jawa Tengah banyak orang Tionghoa mengungsi ke Lasem. Orang Tionghoa Lasem bekerja sama dengan orang Jawa melawan Belanda. Dalam pemberontakan Lasem ini Tan Kee Wie memimpin armada penyerangan terhadap penjajah Belanda lewat laut. Mereka berhasil membuyarkan tangsi Belanda di Rembang. Dari kota Juwana mereka hendak menyerang Belanda di Jepara. Sampai di pesisir Tayu mereka dapat tambahan orang Tionghoa Tayu yang juga siap menyerang Belanda di Jepara. Namun jung yang dinaiki Tan Kee Wie ditembaki meriam Belanda dan beliau gugur di tahun 1742.
Tentara VOC dari Jepara diadang oleh pemberontak Lasem pimpinan Mayor Oey Ing Kiat. Sementara sahabatnya, Raden Panji Margana, bertempur dengan penjajah Belanda dan antek-anteknya di Narukan dan Karangpace. Namun Raden Panji tewas, dan begitu Mayor Oey Ing Kiat tahu ia kehilangan Raden Panji, sahabatnya itu, ia menerjang Belanda habis-habisan, hingga akhirnya gugur tertembak.
Jika para pemimpin bersuku “pribumi” yang gugur melawan penjajah dikatakan sebagai pahlawan nasional, sudah semestinya yang dari ras Tionghoa seperti Tan Kee Wie dan Oey Ing Kiat juga, sehingga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi nasionalisme orang Indonesia keturunan Tionghoa.
Berdasarkan sikap terhadap Penjajah Belanda, warga Tionghoa dapat dibagi menjadi tiga model kelompok. Pertama, Sin Po dan selanjutnya Pao An Tui, yang berkiblat ke Tiongkok. Kedua, Chung Hua Hwee (CHH) yang berorientasi kepada pemerintah Belanda. Dan ketiga, Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang merupakan gerakan nasionalis Indonesia. Namun tiga kelompok ini sering tak dibedakan dengan baik. Sejak zaman Diponegoro hingga peristiwa Mei Kelabu 1998 identitas Cina (Tionghoa) cenderung otomatis dicap sebagai “musuh” pribumi. Padahal itu dilandasi kebencian akibat (1) politik Penjajah Belanda yang menempatkan kalangan Tionghoa sebagai minoritas perantara yang memungut upeti, (2) asumsi RRC sebagai sponsor G-30S PKI (yang kini tak lagi relevan), serta (3) diskriminasi gaji karyawan pribumi di perusahaan milik Tionghoa, yang merupakan balasan atas diskriminasi oleh pemerintah (melalui sekolah negeri, PNS, dan ABRI). Akibatnya banyak Tionghoa yang nasionalis pun juga menjadi korban.
Setelah Indonesia merdeka pun tak sedikit (peranakan) Tionghoa yang gigih berjuang memajukan Indonesia, seperti Yap Thiam Hien (hukum), Arief Budiman (sosial budaya), Kwik Kian Gie (ekonomi), Hermawan Kertajaya (pemasaran), Yohanes Surya (pendidikan), Mario Teguh (pengembangan diri), hingga Dr Lie A. Darmawan (dokter sosial pemilik rumah sakit apung). Juga banyak tokoh mengharumkan nama Indonesia dalam bidang budaya, sastra, dan seni, antara lain Jaya Suprana, Kho Ping Ho, Didik Nini Thowok, hingga Agnes Monica serta Dedy Cobuzier. Dalam bidang olah raga ada atlet legendaris dunia, seperti Rudy Hartono, Christian Hadinata, Susi Susanti, dll. Pada saat mereka menyerahkan segala daya dan juang mereka demi Indonesia. Sedikit pun tidak berpikir bahwa mereka adalah “setengah Indonesia”.
Memang tidak sedikit pula Tionghoa Indonesia yang lebih memikirkan kekayaan dan kepentingan keluarganya. Namun bukankah itu juga terjadi di kalangan “pribumi”? Lihat saja orang-orang yang ditangkap KPK. Lepas dari gaya komunikasinya yang spontan dan blak-blakan, rekam jejak Ahok masih lebih nasionalis dan merakyat daripada banyak pejabat lain yang mengaku Indonesia “asli”.
Untuk menghapuskan diskriminasi dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, ada tugas besar bagi pemerintah Jokowi-JK untuk selalu hadir menjamin amanat konstitusi untuk kesetaraan hak warga negara. Tindakan tegas hendaknya bukan saja kepada pelaku diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa, namun juga terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh keturunan Tionghoa, seperti oleh pengusaha. Dengan demikian “Sumpah Pemuda” mewujud untuk memutus rantai “lingkaran setan” luka dan dendam, dan seluruh rakyat dapat menikmati kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi.
Hidup Persatuan Indonesia!
Hananto Kusumo adalah Pembina Yayasan Pengembangan Potensi Kawasan dan Kebangsaan (YPPKK)

Bertemu Herzog, Menlu Inggris: Jelas Israel Akan Tanggapi Se...
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengatakan jelas bahwa Israel...