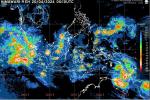Kapan Nisan akan dipasang?

SATUHARAPAN.COM - Mama diam-diam ke Hanga Loko Pedae malam-malam…
Hanga Loko Pedae atau ‘celah kali kering yang selalu dibicarakan’ justru menyimpan diam yang paling dalam. Hanga Loko Pedae terletak di Pulau Sabu-Raijua Nusa Tenggara Timur, dapat dijangkau dengan sejam naik pesawat atau 12 jam memakai kapal laut dari Kupang.
Jika nama pulau ini tidak pernah kita dengar, apalagi kisah pembantaian sistematis yang dikomando dari Jakarta sejak 1965. Pasukan tentara dari Kupang sengaja didatangkan untuk melakukan eksekusi pada orang-orang yang tidak tahu menahu dan berada ribuan kilometer dari Tempat Kejadian Perkara baik sebelum, sesaat maupun sesudah kejadian 1 Oktober 1965. Pada 29 Maret 1966, 31 saudara setanah air Indonesia, 13 di antaranya adalah guru-guru terbaik di pulau terpencil ini dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan yang diduga anggota, dieksekusi baik dengan tembakan maupun penggalan di kepala tanpa pengadilan.
Hanga Loko Pedae adalah padang rumput yang indah, beberapa kuda tampak merumput dan bukit-bukit hijau di kejauhan ikut menanggung kegelapan pembunuhan massal ini. Tidak ada yang bisa dan boleh dibicarakan dari peristiwa itu atau menanam tanda-tanda pengingat, apalagi nisan, bagi anak-anak yang ditinggalkan untuk sekadar meletakkan bunga. Tidak ada upacara dan doa yang bisa dikekalkan sebagai pengucap selamat jalan. Sunyi menjadi pengubur tragedi.
Beberapa perempuan yang suaminya dibunuh dan menjadi korban sampai sekarang tidak mampu menceritakan peristiwa ini bahkan pada anak-anak mereka apalagi kepada orang lain, seakan-akan bercerita akan membuat mereka ikut terbunuh. Mereka yang telah punya keberanian memilih untuk terus bercerita tentang peristiwa yang masih terasa seperti kemarin, karena 45 tahun mereka telah berjuang menahan airmata untuk tidak jatuh, di tengah pengasingan, sosial, ekonomi dan administratif di negeri sendiri. Di renta usia dan tangan yang telah bergetar, apalagi yang harus ditakutkan?
Hanga Loko Pedae pada sebuah sore bulan Maret 2014, seorang mama menitikkan kembali airmata, ketika seorang laki-laki berkata ‘saya tidak ingat lagi di sebelah mana ayahmu diletakkan dalam susunan jasad tiga puluh satu orang itu, tubuh saya sudah penuh darah…. Opa Barapa, kami menyebutnya, adalah seorang guru yang dipaksa menggiring kawan-kawannya untuk dieksekusi.
Hanga Loko Pedae hanyalah satu dari sekian banyak kuburan massal yang tersebar di seluruh Indonesia, dari yang telah digali dan terbukti di desa Dempes, Wonosobo tahun 2000 sampai yang hanya diceritakan dengan berbisik. Kuburan massal Wonosobo berisi 26 orang. Saat itu, anak perempuan bernama Sri akhirnya dapat menemukan tulang-tulang ayahnya yang hilang dan menguburkannya dengan layak sebagai penutup duka.
Di Gua Grubug Gunung Kidul Jogjakarta Yogyakarta, ratusan warga negara Indonesia dieksekusi dan dibuang ke gua dengan kedalaman 60 meter, dan mereka pun terkubur baik dalam keadaan hidup atau mati atau terhanyut di sungai di dasar gua yang bermuara ke laut selatan. Pantai Masceti Bali dengan empat lubang yang berisi masing 45 orang, tanpa tanda sampai kini, hanyalah satu dua nama kuburan massal korban 1965 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tidak ada satu suku atau agama pun di Indonesia yang tidak meletakkan kematian sebagai sesuatu yang sakral. Menghormati orang tua yang sudah meninggal dan melakukan prosesi duka adalah bagian dari kemanusiaan Indonesia. Beberapa suku memang dapat melakukannya tanpa jasad mereka yang meninggal, namun mayoritas warga Indonesia membutuhkan upacara penguburan atau pembakaran jasad atau setidaknya upacara mengenang kematian. Orang Jawa bahkan melakukannya berkali-kali; tiga, tujuh, seratus, setahun dan seribu hari sesudahnya.
Jika terpidana mati yang terbukti bersalah di pengadilan pun dikuburkan dengan layak dan penemuan satu korban pembunuhan yang ditanam di kebun atau disimpan di lemari pendingin adalah skandal nasional hari ini, maka jutaan korban pembunuhan massal 1965 dianggap tidak ada, bahkan keluarganya pun bahkan tidak dapat menyatakan kehilangannya apalagi melakukan proses duka sebagaimana mestinya.
Generasi ketiga dari korban-korban pembantaian tersebut mungkin tidak tahu atau tidak pernah tahu bagaimana kakek mereka mengalami ketidak adilan yang berujung pada kehilangan nyawa, tanpa pengadilan bahkan tanpa catatan. Belum lagi ribuan yang dipenjara tanpa proses. Bangsa Indonesia berhutang nyawa dan berhutang kebenaran pada generasi ketiga ini. Alih-alih memaparkan mereka dengan kebenaran, mereka dicekoki dengan manipulasi sejarah; bagaimana kematian tujuh jendral yang bahkan tidak jelas nama-nama siapa saja pelakunya harus dibalas dengan membunuh tiga juta orang (menurut Sarwo Edhi sendiri)? Sementara generasi kedua yang harus menyaksikan orang tua mereka hilang dan menyandang cap anak komunis, kebanyakan masih memilih diam sebagai cara untuk bertahan hidup di tengah masyarakat secara normal.
Rekonsiliasi menjadi begitu sulit dengan amnesia yang akut dari bangsa ini. Jangankan peristiwa 1965, bahkan peristiwa 1998 pun sudah lupa. Pengalaman rekonsiliasi dari Afrika Selatan atau Jerman, juga tidak banyak membantu karena penduduk kulit hitam dan bangsa Yahudi di akhir konflik bisa dikatakan keluar sebagai pihak yang mempunyai posisi tawar, sementara ibu-ibu Gerwani dan bapak-bapak korban kamp konsentrasi Pulau Buru sampai akhir hidupnya bahkan tidak mendapat sekadar penjelasan tentang kejahatan yang mereka lakukan, jika memang ada. Jika menjadi anggota bahkan simpatisan partai yang resmi pada masanya adalah kejahatan yang layak dihukum mati atau dipenjara atau diasingkan, maka fenomena golput dan fenomena apatisme politik hari ini hanyalah residu akhir dari trauma dan ketakutan kolektif terhadap kekerasan Negara. Negara yang mampu membantai warganya sendiri dengan sistematis dan vertikal untuk menunjukkan kekuasaannya selama hampir limapuluh tahun.
Namun tidak ada kata terlambat dan harapan masih ada. Tahun 2012, Komnas HAM telah menyatakan penghukuman secara sistematis pada mereka yang diduga anggota atau simpatisan PKI merupakan pelanggaran HAM berat, meskipun kelanjutan dari proses ini masih belum jelas. Pemerintah Indonesia adalah pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap kesalahan pemerintah di masa lalu.
Rekonsiliasi membutuhkan tidak hanya fakta kebenaran dari korban namun juga fakta pengakuan dari pelaku, permintaan maaf secara resmi kepada korban secara nasional, dan pelurusan sejarah. Usaha individu dan komunitas untuk melakukan rekonsiliasi di akar rumput telah muncul di sana-sini, bahkan dilakukan oleh generasi ketiga. Tujuannya terutama bukan sebagai penghukuman terhadap pelaku lapangan namun pemulihan martabat korban dan pelurusan sejarah. Tahun ini, rakyat Indonesia akan memilih pemerintahan baru yang berani melakukan rekonsiliasi, semoga!
Desmond Tutu menyatakan bahwa rekonsiliasi yang sesungguhnya akan membuka keburukan, kejahatan, luka dan kebenaran. Mungkin terkadang akan membuat situasi buruk harus dilewati, namun risiko ini harus diambil untuk tujuan yang lebih mulia, karena pada akhirnya, hanya dengan konfrontasi yang jujur dengan realita, kesembuhan bangsa yang sesungguhnya akan terjadi.
Penulis adalah penyair, kini bekerja sebagai tenaga penerjemah lepas

Bertemu Herzog, Menlu Inggris: Jelas Israel Akan Tanggapi Se...
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron, mengatakan jelas bahwa Israel...