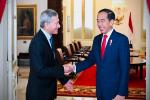Luther yang Terlupakan
Percikan Konferensi Internasional Ketiga (7 - 10 Januari 2017). Radikalisasi reformasi di Wittenberg dalam rangka memperingati 500 Tahun Reformasi Martin Luther 1517-2017.

SATUHARAPAN.COM – The Forgotten Luther adalah salah satu judul buku yang ditulis oleh sekelompok teolog menjelang Konferensi Internasional Ketiga Radikalisasi Reformasi di Wittenberg Jerman. Judul itu langsung membuat saya terhenyak di dalam konferensi. Demi memuaskan keterhenyakan saya, Dr Conrad Braaten, pastor senior dari Gereja Reformasi di Capitol Hill Washington DC, rekan panelis saya di Wittenberg, menghadiahkan buku tersebut kepada saya, sehabis dia mempesentasikannya.
Judul di atas terhitung aneh. Bagaimana dapat dipahami “Luther yang Terlupakan”, padahal sepanjang lima ratus tahun di lima benua nama Martin Luther (bedakan dari Martin Luther King Jr, Pen.) terus bergema melalui puluhan ribu buku? Bagaimana dapat dipahami kalau Luther terus menerus dikaji dalam seminari dan seminar, dalam telaah dan tesis oleh semua denominasi Protestan?
Bagaimana mungkin Luther “terlupakan” ketika nyaris setiap Kristiani dan non-Kristiani mengenalnya, setidaknya sebagai sosok sejarah? Bagaimana mungkin Luther “terlupakan” sementara setiap aspek karakter Luther telah dituliskan lebih dari siapa pun dalam sejarah gereja?
Bagaimana dapat dipahami Luther “terlupakan”, kalau pada tahun 2003, ZDF, salah satu stasiun televisi Jerman melakukan kontes tentang 10 tokoh Jerman terbaik dan Luther keluar sebagai nama nomor dua, sesudah nama Kanselir Jerman pascaperang Konrad Adenauer? Bagaimana mungkin Luther “terlupakan” ketika kota kuno dan terpencil tempat Luther seperti Wittenberg dijadikan situs historis PBB?
Bagaimana mungkin “terlupakan” ketika situs-situs Luther di Wittenberg beberapa tahun belakangan menuju peringatan 500 tahun Reformasi ini menjadi sapi perah turisme yang dimeriahkan dengan cenderamata sosok Luther kecil, yang merupakan cenderamata paling cepat laku dari produsennya? Belum lagi segala macam barang, pakaian, dan makanan, yang dibubuhi gambar dan nama Luther. Judul ini memang terasa radikal.
Kata “radikal” dalam Radikalisasi Reformasi bukanlah merujuk kepada kekerasan seperti yang belakangan ini menjadi nuansa kata tersebut; seperti dalam ungkapan “kelompok radikal”. Sebaliknya radikalisasi di sini berarti melihat Reformasi Luther sampai ke akarnya (radiks) dan melihat relevansinya untuk konteks dan zaman kita sendiri. Misalnya tentang:
Bir Luther, Luther dan Bir
Apa yang orang lupa antara lain adalah sementara Jerman adalah negeri peminum bir, Luther tenggelam juga di dalamnya selaku orang Jerman umumnya. Luther menuliskan tentang bir pada beberapa suratnya. Salah satunya surat kepada istrinya, tentang betapa ia merindukan bir buatannya sendiri di rumah. “Aku tak habis memikirkan betapa bagus anggur dan bir yang kumiliki di rumah, seperti juga seorang istri cantik ... kamu akan berbaik hati mengirimkan kepadaku seluruh persediaan anggur dari gudang dan semua botol bir yang ada padamu.”
Namun, sebagai reformator ia membuat bir Jerman mendukung wahana industri kecil rumahan masyarakat, sehingga sampai dewasa ini terkenallah “bir Luther”. Apa yang Luther katakan tentang bir? “Siapa pun yang minum bir, ia cepat tidur; siapa pun yang tidur lama, tidak berdosa; siapa pun yang tidak berdosa, masuk surga! Jadi, mari minum bir!”
Tentu saja minum bir sebagai kegiatan sosialita bukanlah dimaksud sebagai sarana bermabuk-mabukan. Pada titik ini saya segera teringat kepada masyarakat Lutheran di Sumatera Utara yang memiliki situasi sejajar. Bukankah Sumatera Utara merupakan negeri peminum tuak? Bukan rahasia bahwa itu sarana sosialita masyarakat. Saya tak tahu setepatnya, namun tidakkah gereja-gereja kita berutang membangun “teologi tuak” ketimbang mencerca dan membiarkannya tidak tersentuh teologi?
Sesungguhnya, masalah kegemaran minum minuman sejenis tuak tersebar luas, seluas di mana gereja-gereja kita hadir dari Sumatera Utara sampai ke Papua? Keinginan membasmi permabukan tidaklah sama dengan membasmi industri kecil rumahan masyarakat yang sudah turun-temurun. Kehadiran sebuah teologi terkait tak salah lagi memang diperlukan. Di mana usaha kecil masyarakat bertumbuh, kapitalisme minuman keras akan kehilangan cengkeramannya untuk mendominasi.
Kembali kepada Luther. “Sederhananya aku mengajar, berkhotbah dan menuliskan tentang Firman Allah. Di luar itu aku tak melakukan apa pun. Lalu sewaktu tidur atau minum bir Wittenberg dengan mitraku Philip (Melanchthon) dan Amsdorf (Nicholaus von), Firman itu begitu melemahkan kepausan seperti yang tak pernah dapat dilakukan oleh para pangeran atau kaisar. Aku tak melakukan apa pun. Firmanlah yang melakukannya.”
Sola Scriptura
Bicara tentang Firman, pemeo Reformasi Luther “Sola Scriptura” dalam dunia Kristiani nyaris menjadi kalimat yang lebih “suci” dari pada kebanyakan kalimat Kitab Suci sendiri. Saya sedikit tercengang ketika seorang rekan peserta konferensi sekaligus rekan gerakan Oikotree global saya dari Brasil, Nancy Cardoso berucap, “Jangan-jangan pada zaman Luther ‘sola scriptura’ merupakan strategi bisnis penjualan Alkitab dari industri percetakan Gutenberg.”
Perlu diketahui, untuk pertama kalinya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa rakyat Jerman dan dibolehkan dibaca oleh semua orang oleh Luther. Ini pertama kalinya orang Kristiani diperbolehkan membaca Alkitab sendiri, seperti semacam demokratisasi membaca kitab suci! Alkitab Jerman ini tersedia bagi masyarakat karena dicetak oleh mesin cetak yang baru ditemukan oleh Gutenberg. Tentu saja Gutenberg sang penemu, tak salah lagi memainkan monopoli pencetakan Alkitab pada masa itu, karena hanya dialah yang memiliki mesin tersebut. Bukanlah mustahil bahwa ‘sola scriptura’ diam-diam dipakai untuk menguatkan monopoli dan strategi bisnisnya.
Konferensi Radikalisasi Reformasi memang menyoroti sejarah dari krisis-krisis dewasa ini. Dewasa ini industri penerbitan Alkitab di seluruh dunia, tidak lagi merupakan otoritas Lembaga Alkitab nasional (National Bible Society) seperti misalnya Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) dan global (United Bible Society). Para penerbit buku yang bermodal masuk ke dalam industri penerbitan Alkitab yang secara global yang bermarket-share miliaran dolar.
Bayangkan saja tentang lembaga Gideons Internasional yang pekerjaannya menyediakan Alkitab di setiap kamar hotel di seluruh dunia. Gideons saja membutuhkan beberapa juta Alkitab untuk misinya dan terus bertumbuh. Dalam dunia di mana empire bisnis berkuasa, bahkan kitab suci pun dijadikan objek bisnis. Gutenberg di masa lampau bukan mustahil menjalani strategi serupa. Seperti di negeri kita sendiri, bahkan kitab suci pun dijadikan objek korupsi resmi.
Buku-buku sejarah gereja kita sering dengan ungkapan lain disebut sebagai “sejarah dogma”. Tak heran kalau yang dapat kita baca di sana adalah pergumulan dogma dan doktrin. Itu pun tak lepas dari siapa penulis dan sudut pandangnya. Orang menjadi lupa, atau lebih tepat terluput dari fakta bahwa Luther sepanjang hidupnya memprakarsai pembaruan ekonomi berbasis kesejahteraan sosial masyarakat.
Luther yang mendedikasikan hidupnya mengkritik ekonomi profit yang tak terkendali dan menciptakan program kesejahteraan sosial, mudah terlupakan karena ia tidak cocok dengan ideologi yang disebutnya sebagai “keserakahan berhias” (dresses up greed). “Betapa terampil tuan serakah dapat berhias seperti manusia saleh, manakala hal itu dibutuhkan, padahal sebenarnya ia adalah pendusta dan pengkhianat” (LW 1532, LW 1521).
Selain yang kita ketahui bahwa Reformasi Luther melawan kerakusan gereja waktu itu yang gencar menjual surat penghapusan dosa (indulgensia), Luther terus menerus menyerang ekonomi profit sehingga antara kegiatan dan teologinya menyatu. Memang konflik kepentingan bersama dan kepentingan pribadi bukanlah barang baru. Tentang itu di zaman Luther ada ungkapan sejajar “Gemeinnutz und Eigennutz” (kebaikan publik dan kepentingan diri sendiri).
Luther menyadari bahwa teologi “Meniru Kristus” (Imitatio Christi) yang populer waktu itu (bahkan sampai sekarang), yang memandang ideal kemiskinan sebagai kondisi Kristiani dan memberi sedekah sebagai jalan membeli surga, sangatlah mendukung ideologi ekonomi profit yang merasionalisasi diri dengan tindakan amal. Namun, tindakan amal itu tak lain dari pada trickledown effect yang kemudian hari mendasari ekonomi Adam Smith di abad ke-18 dan masih menjadi dasar ideologi sampai hari ini.
Seorang penulis menggambarkan proses ini secara menjijikkan, “Jika seekor kuda diberi makan cukup gandum, maka akan ada sesuatu di jalanan bagi burung gereja”. Dengan kalimat klise “iman dibentuk melalui amal”, maka tak akan ada alasan ataupun semangat untuk membongkar ekonomi tak adil yang menyebabkan kemiskinan.
Ada ungkapan lain yang menggambarkan ini. “Kemiskinan seseorang ditentukan oleh Allah, siapa mengubahnya berarti melawan Allah”. Mungkin bertolak dari doktrin seperti ini ada gerakan Kristiani global yang rajin memberi makan orang kelaparan, membantu orang miskin yang kedinginan dan tersudut, tetapi tak pernah bertujuan mengubah kemiskinan mereka atau ketidakadilan terhadap mereka.
Situasi yang dihadapi Luther kira-kira sama dengan yang dihadapi oleh Uskup Agung Brasil Dom Helder Camara, yang berucap “Jika aku memberi makan orang miskin, mereka menyebutku orang kudus. Jika aku bertanya mengapa orang miskin tak punya makanan, mereka menyebutku Komunis”. (Camara, 2009). Luther lebih beruntung daripada Camara, karena Karl Marx dan Komunisme baru akan lahir 400 tahun kemudian.
Judul kita, tidak salah menyebut “Luther yang Terlupakan”, karena sampai sekarang kita umumnya bersemangat membantu orang miskin, tetapi tak bersemangat mengubah ketidakadilan yang menimpa mereka. Semangat itu kalah jauh dengan semangat membangun gedung-gedung gereja, yang notabene akan dinikmati oleh kita sendiri.
* Penulis adalah Pendeta Emeritus GKI
Editor : Sotyati

Diam-diam Ukraina Gunakan Rudal Jarak Jauh dari AS, Serang W...
WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Ukraina untuk pertama kalinya mulai menggunakan rudal balistik jarak ...