Mengembalikan Roh Gerakan Oikoumene
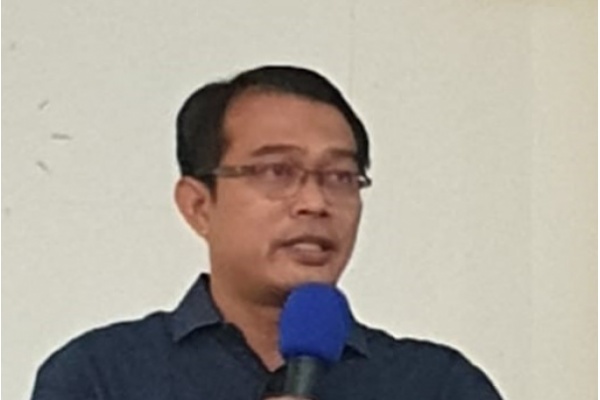
SATUHARAPAN.COM – Tanggal 8–13 November nanti di Waingapu, Sumba Timur, akan berlangsung perhelatan akbar Sidang Raya ke-XVII PGI. Ini merupakan pertemuan puncak lima tahunan sinode gereja-gereja yang menjadi anggota PGI. Di situ berbagai persoalan dan tantangan yang menerpa gereja-gereja maupun perjalanan bangsa dan negara diperbincangkan. Dan gereja-gereja akan menetapkan arah serta strategi lima tahun ke depan lewat dokumen yang dikenal sebagai Pokok-pokok Tugas dan Panggilan Bersama (PTPB), sebagai dokumen pertama dan utama dalam Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG).
PTPB memang ditempatkan sebagai urutan pertama dalam LDKG. Posisi tersebut sekaligus menegaskan sifat strategis dokumen itu dalam keseluruhan gerak oikumenis yang memintal sejarah gereja-gereja di tanah air. Sebab di dalam PTPB, gereja-gereja menggumuli tantangan serius yang dihadapi oleh bangsa dan negara maupun gereja dalam lima tahun ke depan, serta strategi yang akan ditempuh untuk menanganinya.
Dalam PTPB 2019–2024 yang akan diputuskan pada Sidang Raya ke-XVII PGI nanti, ditengarai ada tiga krisis dan satu tantangan fundamental yang akan menentukan arah kehidupan bangsa dan negara maupun gereja-gereja ke depan.
Pertama adalah krisis kebangsaan yang tercermin dalam makin rapuhnya sendi-sendi persatuan, polarisasi masyarakat yang makin lebar serta ”politik transaksional” yang makin mewarnai jagat perpolitikan kita dewasa ini.
Kedua adalah krisis ekologi yang sudah mengarah pada ”kiamat ekologis” karena perusakan dan penjarahan sumber daya alam di banyak tempat, sebagai ekspresi kerakusan tanpa batas para elite politik dan ekonomi.
Ketiga adalah krisis keesaan yang sangat terasa dalam kehidupan gereja-gereja di tanah air. Sudah lama, seperti tercermin dalam penelitian Biro Litkom-PGI selama 2013, gerakan oikoumene mengalami kemandegan serius. Oikoumene sudah menjadi sekadar ”urusan birokrasi gereja” tanpa punya relevansi pada dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Begitu juga, prinsip dasar ”keesaan in action” hanya berhenti menjadi slogan kosong, sementara dalam praktiknya banyak konflik-konflik internal gereja justru terjadi yang kerap berakibat pada perpecahan dalam Tubuh Kristus. Dan akhirnya, sangat kentara ketiadaan kader-kader oikoumenis yang juga mampu menjadi agents of change dalam masyarakat.
Selain ketiga krisis tersebut, PTPB juga mencandra satu tantangan fundamental yang dampaknya akan sangat menentukan di masa depan: revolusi digital yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan sarana telekomunikasi. Sudah banyak pengamat dan pakar yang mencandra, bahwa revolusi digital tersebut akan mengubah sama sekali lanskap sosial, poltik, ekonomi dan budaya—bahkan kehidupan sehari-hari kita!—dunia mendatang.
Memang benar, kita di Indonesia baru mengalami “dampak pinggiran” dari revolusi tersebut. Kita sudah menyaksikan, dalam rangkaian pemilihan umum, baik pada tingkat pemilukada maupun pemilihan presiden, bagaimana peran media sosial serta penyebaran hoaks makin lama makin menentukan pilihan-pilihan politik yang nantinya mengarahkan kebijakan publik, maupun menjadi salah satu faktor penting yang menyumbang pada polarisasi dalam masyarakat.
Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita makin tergantung pada layanan online, mulai dari berpergian, memesan makanan, tiket sampai layanan kesehatan dan, bahkan, konseling kejiwaan. Tidak lama lagi—Klaus Schwab, pendiri dan direktur World Economic Forum, bahkan memperkirakan tahun 2025 sebagai ambang batas fusi teknologi fisik, biologis dan digital—revolusi tersebut akan makin mempengaruhi dan menentukan kehidupan sehari-hari kita, baik sebagai pribadi, bangsa, negara, maupun gereja. Sudah siapkah kita?
Mengingat begitu luasnya krisis dan tantangan yang dihadapi, menurut saya Sidang Raya ke-XVII PGI November nanti menempati posisi yang sangat strategis dan fundamental guna mempersiapkan gereja-gereja di Indonesia. Sangat disayangkan jika perhelatan besar itu menjadi sekadar bermakna seremonial dan berlangsung business as usual di tengah krisis dan tantangan itu, sebagaimana biasa terjadi selama ini. Akibatnya, alih-alih bergumul secara serius dengan krisis dan tantangan yang dihadapi, orang hanya menaruh perhatian pada komposisi kepengurusan PGI mendatang. Dan LDKG yang dihasilkan, terutama PTPB, menjadi rumusan indah, tetapi tidak pernah menjiwai kehidupan gereja-gereja di tanah air.
Menurut saya, sudah saatnya kita semua memberi perhatian penuh dan serius pada krisis dan tantangan di atas. PGI harus menimba kembali spirit dasar, yakni ”roh” yang menjiwai gerakan oikoumene, dan berperan aktif sebagai lokomotif yang menarik gereja-gereja untuk bersama-sama menggumuli krisis dan tantangan itu. Dan ini membutuhkan perubahan mendasar bukan saja pada tataran kepemimpinan, tetapi juga pola dan mekanisme kerja. Oikoumene adalah gerakan bersama yang memperjuangkan agar dunia ini layak didiami bersama-sama oleh seluruh makhluk!
Selama ini, setelah aktif sebagai Sekretaris Eksekutif KKC (Keadilan dan Keutuhan Ciptaan) di PGI periode 2015–2018, bersama beberapa rekan saya mendirikan Paritas Institute. Lembaga ini didedikasikan pada perjuangan HAM dan saling pengertian antarkelompok. Kami telah melakukan pelatihan dan membentuk komunitas ”penggerak perdamaian” di 15 kota. Dari situ saya belajar memahami betapa dalamnya krisis dan tantangan yang kita hadapi: polarisasi masyarakat makin melebar, ekologi kita makin hancur, sementara kiprah tokoh-tokoh Kristen di ruang-ruang publik makin sunyi. Padahal tantangan yang kita hadapi makin berat, walau saya juga melihat ada banyak peluang, seperti misalnya program perhutanan sosial yang, sayangnya, sama sekali tidak dimanfaatkan oleh gereja-gereja.
Karena itu saya melihat PGI harus mengembalikan roh gerakan oikoumene untuk mendorong proses transformasi dalam masyarakat. Untuk itu, saya melihat tiga program strategis yang seharusnya dikerjakan oleh kepemimpinan PGI mendatang. Pertama, mempersiapkan kader-kader oikoumenis lintasdenominasi yang juga siap memainkan peran transformatif dalam masyarakat. Mereka diharapkan akan mengisi ruang-ruang publik dan menjahit kembali kehidupan bersama yang terkoyak oleh sekat-sekat primordial. Merekalah yang akan ikut menentukan transisi politik tahun 2024 nanti. Mereka pula yang akan menjadi simpul-simpul gerakan oikoumene yang mampu mengatasi sekat-sekat antar-denominasi.
Kedua, mendorong dan mempersiapkan gereja-gereja dalam menghadapi tantangan revolusi digital yang akan mengubah seluruh lanskap kehidupan kita. Di sini pelatihan mengenai digital literacy, membuka ruang partisipasi yang makin luas bagi keterlibatan generasi milenial, membangun ketahanan dan produktivitas ekonomi jemaat yang berbasis digital, harus menjadi prioritas. Kerja sama antargereja di sini sangat dibutuhkan. Dan PGI seharusnya mampu menjadi simpul jejaring kerja yang dapat melibatkan gereja-gereja di tanah air, baik anggota PGI maupun tidak.
Akhirnya, ketiga, PGI harus memiliki sikap dan posisi yang jelas dan tegas terhadap perubahan sosial-politik sekarang. Ini menuntut PGI melakukan pembelaan terhadap korban-korban pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua, praktik-praktik diskriminatif yang masih terus terjadi pada kelompok rentan, serta mendorong pemerintah bersikap tegas terhadap perilaku kerakusan tanpa batas yang ditunjukkan oleh para elite politik dan ekonomi. Tanpa ketegasan itu, kerakusan tanpa batas hanya akan mempercepat “kiamat ekologis” bagi kita semua!
Semoga Allah Kehidupan menyertai perjalanan PGI ke depan.
Editor : Yoel M Indrasmoro

Tips Bagi Pasangan Sebelum Menikah
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Psikolog klinis anak dan remaja dari Lembaga Psikologi Terapan Universita...
































