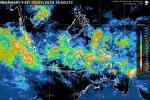Setahun Kamisan: Merayakan Perbedaan

“Tanpa perbedaan, tidak ada kemajuan. Sebab, kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang disebut cukup sampai kita mengetahui apa yang disebut lebih dari cukup.”
( William Blake, 1757-1827)
SATUHARAPAN.COM – Bermula dari kegelisahan tentang ketiadaan ruang diskusi kritis dan tradisi literasi, mendorong segelintir orang, dengan latar belakang yang beragam, menggagas diskusi yang dimulai pertama kali di sebuah teras kontrakan rumah pada Kamis Malam (4/9/14). Diskusi yang membincangkan banyak hal ini pada gilirannya dikenal dengan nama Diskusi Kamisan, karena rutin ditaja setiap Kamis malam
Kini sudah setahun terlewati, Kamisan yang dihuni oleh warga dengan latar belakang identitas dan ragam pemikiran, bergerak terus menerus untuk melahirkan kreasi dan inovasi sebagai ikhtiar dari komitmen memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk kehidupan dan kemanusiaan. Kamisan telah melahirkan lahir banyak mimpi, termasuk mimpi besar membangun peradaban kota, sebuah peradaban alternatif yang kelahirannya dibidani warga kota, mengutamakan partisipasi-kesetaraan daripada instruksi-hirarkis, menempatkan lebih tinggi prestasi daripada pristise, mendahulukan gagasan daripada bualan-materi.
Mimpi besar tentang sebuah peradaban kota dimana warga kota mampu menyelenggarakan kebebasan, menjalankan keadilan, menjaga kesejahteraan dan mengundangkan persamaan. Mimpi besar yang tidak pernah digantungkan kepada kekuasaan dan elit kota, tetapi dikerjakan sendiri oleh komunitas ini, mereka tidak hanya berdiskusi, berbincang dan berpikir, tetapi juga membuka baju dan menanggalkan sepatu, turun ke parit mengangkat batu, mendaratkan cangkul ke tanah, memanggul pasir dan membangun rumah.
Melawan Takdir Sosial
Kehadiran Kamisan, menolak ketergantungan, membangun kemandirian dan gotong royong adalah tradisi yang telah lama ditinggalkan oleh warga kota. Kamisan yang mencoba kembali menghidupkan tradisi-tradisi itu, mengundang nada sumbang penuh pesimis, sebagai hal yang tak mungkin terjadi di zaman yang serba hedonis, serba internet, serba modern, serba instan dan serba sendiri-sendiri. Sehingga pekerjaan itu seolah “melawan takdir sosial”.
Namun, pelan tapi pasti, diskusi yang awalnya dipandang sebelah mata ini menjadi sebuah diskusi yang cukup dikenal. Banyak kalangan melirik kehadiran komunitas diskusi ini mulai akademisi lokal, birokrat, nasional bahkan peneliti asing berdatangan untuk menikmati hangatnya kopi dan berbagi pengetahuan. Edisi Diskusi ke 55 misalnya, seorang peneliti doktoral asal Mauritania mengajak berdiskusi mengenai topik penelitiannya melalui media skype.
Tagline semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah dipinjam untuk memberikan inspirasi bahwa siapapun bisa menjadi narasumber dalam setiap diskusi yang digelar. Terkadang petani, disk jockey justru didaulat menjadi narasumber berdasarkan kesesuaian topik yang dipilih peserta diskusi. Narasumber tak identik dengan jejeran titel yang diperolehnya, tak jarang mereka yang titelnya berderet juga harus gigit jari menghadapi “kerasnya” perdebatan di diskusi kamisan.
Kamis (3/9/15) adalah seri ke-54 yang menandai kehadiran diskusi ini tepat satu tahun. Diskusi ini perlahan bergerak menjadi gerakan sosial baru yang anti mainstream dan terkadang berpikir out of the box. Menariknya diskusi yang diikuti orang berbagai kalangan dan latar belakang aliran justru melahirkan menjadi dinamika tersendiri. Pada gilirannya setiap orang justru semakin menghargai perbedaan. Implikasinya gagasan-gagasan baru lahir dan berkembang layaknya bunga yang tumbuh subur di taman.
Dari Ide Menuju Praksis
Penulis teringat pesan salah satu begawan hukum Indonesia yang telah berpulang yakni Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, baginya pendidikan adalah soal “educating the brain and heart” pendidikan itu mendidik otak dan hari sekaligus. Soetandyo menyayangkan banyak orang cakap cerdas berpengetahuan tinggi justru siap bekerja dan dipekerjakan sebagai ahli “bayaran”.
Keprihatinan akan kosmologi intelektual di kota yang menyandang predikat Kota Pendidikan inilah yang menjadi keresahan sekaligus tantangan bagi para intelektual yang sesungguhnya bertugas menjadi lentera peradaban. Komunitas ini berniat tak hanya menjadi intelektual bayaran atau intelektual jongos melainkan intelektual yang mampu menjadi lentera perubahan.
Komunitas diskusi ini sejak awal memahami bahwa persoalan-persoalan kota tak selesai diruang-ruang diskusi. Sejumlah inisiasi lahir dari diskusi, mulai dari membuat portal jurnalisme warga, gerakan pungut sampah, membuat bank sampah, mendirikan rumah bersama tempat komunitas berkumpul dan berkreasi, mendorong lahirnya penerbitan lokal, lembaga riset lokal hingga memproduksi album.
Komunitas ini seakan hendak berlari melampaui kemampuan dan usianya melewati berbagai tantangan zamannya. Bila pendanaan identik menjadi kendala, komunitas ini justru memaknai pendanaan adalah nomor sekian, karena ini bukan sekedar bsia atau tidak bisa tapi persoalan mau dan tidak mau.
Pergeseran ide menuju praksis menandai era baru tradisi intelektual di Kota Metro. Tradisi gotong-royong dan kerjasama ini seakan hendak membuktikan pandangan Michel de Certeau dalam The Practice of Everyday Live yang mengatakan bahwa kolaborasi sesungguhnya adalah soal praktik yang diuji terus-menerus. Gagasan menjadi kehilangan makna ketika kehilangan ruang dan medan praksisnya.
Gagasan-gagasan baru sekaligus ikhtiar-ikhtiar baru yang dilahirkan seakan hendak menerjemahkan gagasan Piere Bourdieu (2002) dalam The Role of Intellectuals Today. Bourdieu menawarkan sebuah pandangan tentang pentingnya gerakan intelektual kolektif, dalam menghadapi tantangan zaman. Gerakan intelektual kolektif, dalam pandangan Bourdieu, merupakan sebuah kelompok intelektual yang masing-masing anggotanya mempunyai kompetensi, saling berhubungan membagi pengetahuan, dan mendukung anggota intelektual lain dalam setiap gerakan membela mereka yang terdominasi. Model gerakan ini menggabungkan beragam kualifikasi dan bakat intelektual di berbagai bidang, yang bekerja sama dan menyediakan wadah interaksi dan komunikasi.
Sejak awal Komunitas Cangkir Kamisan menekankan pada kemandirian intelektual dan mengakomodasi berbagai aliran pemikiran dan perspektif. Gerakan ini lahir dan berkembang dari cita-cita meningkatkan kesadaran publik, dan saling bekerja sama memberikan jawaban, atas problem-problem yang dihadapi di setiap arena yang mereka tempati.
Ke depan tantangan komunitas ini akan semakin besar seiring dengan semakin banyaknya orang yang bergabung. Tantangan terbesar adalah soal mempertahankan cara pandang, independensi terhadap kekuasaan dan juga bagaimana perlahan mengubah pandangan masyarakat tentang kota dan demokrasi ditingkat lokal. Tugas-tugas intelektualnya terus meningkat dari sekedar membangkitkan tradisi literasi menjadi aksi-aksi nyata yang memiliki dampak bagi perkembangan peradaban kota, khususnya Kota Metro.
Jika kesadaran tentang pentingnya kerjasama dalam kesetaraan dan keragaman budaya ini berhasil ditanamkan di setiap warga, akan terbangun komunitas masyarakat yang berkarakter demokratis dan tidak gampang melontarkan prasangka-prasangka negatif atas adanya perbedaan budaya. Jika karakter masyarakat demokratis berhasil terbentuk, maka harapan untuk membangun masyarakat multicultural di Indonesia tidak lagi sekedar wacana. Semoga, komunitas Kamisan yang telah berjalan selama setahun ini, selalu memiliki cara dan alasan untuk terus merayakan perbedaan dengan riang gembira.
Penulis adalah penggiat forum diskusi Cangkir Kamisan

Benyamin Netanyahu Menolak Rencana ICC Keluarkan Surat Perin...
YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Pengadilan Kriminal I...