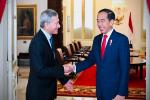Plagiarisme dan Terbunuhnya Kreativitas
Plagiarisme marak di mana-mana. Apalagi dengan akses internet untuk penerbitan daring. Padahal plagiarisme adalah kejahatan intelektual paling parah dan memalukan.

SATUHARAPAN.COM - Bagi penggemar lagu-lagu rock dari band legendaris asal Inggris, Led Zeppelin, pasti mengenal lagu sepanjang masa, Stairway to Heaven. Sejak 2014 mereka dituduh menjiplak lagu grup band Spirit, Taurus. Pihak Spirit menuntut Led Zeppelin membayar kompensasi 40 juta dollar (Rp. 523 miliar) akibat kerugian yang mereka derita.
Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, diputuskan Stairway to Heaven adalah karya orisinal. Delapan panel juri menyatakan unsur asli lagu Taurus tidak mirip dengan Stairway to Heaven (kompas.com, 24/06/2016). Dengan demikian kredibilitas Led Zeppelin sebagai grup hard rock terbesar dalam sejarah tetap terjaga.
Budaya Kanibal
Baru-baru ini Dirjen Sumberdaya Iptek dan Dikti (SDID) Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi merilis data 10 ribu dosen yang mengikuti sertifikasi, sebanyak 6 ribu di antaranya tidak lulus (beritasatu.com, 15/07/2016). Salah satu kendala terjadi saat pengisian analisis diri. Kebanyakan dosen tidak melakukannya dengan benar alias mencontek dari data dosen sebelumnya atau mengambil dari internet dan data publikasi.
Mereka tidak sadar saat ini software pengecekan plagiarisme atau penjiplakan sudah mulai umum digunakan. Ada beberapa software untuk melihat keaslian tulisan seperti Duplichecker, Plagiarisma.net, Plagium, SeeSource, dll. Melalui sebuah obrolan dengan seorang dosen tim pengecekan keaslian tulisan, ia angkat tangan melihat praktik plagiarisme di kalangan dosen hingga lebih 50-70 persen. “Kalau 30 persen diplagiasi masih kita toleransi lah”, katanya.
Hal ini ironi bagi dunia perguruan tinggi Indonesia. Tridarma perguruan tinggi mengharuskan dosen mengembangkan kemampuan bukan hanya mengajar, tapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam praktiknya, pengabdian masyarakat dosen pasti berhubungan dengan dunia akademis seperti panelis seminar, konsultan, atau fasilitator.
Demikian pula kemampuan dosen mengajar bukan hanya berceramah, tapi mempersiapkan bahan/buku ajar. Bahan ajar selayaknya bukan hanya mengcopy-paste dari buku referensi, tapi mengulas, memperbaharui, dan membuat catatan khusus. Realitas ini khas dijumpai di Indonesia, termasuk di kampus saya. Ada dosen mengajar hingga lebih 20-an SKS (satuan kredit semester) tapi tidak menghasilkan bahan/buku ajar apapun.
Keterampilan menulis menjadi tuntutan utama, terlebih dosen berbasis ilmu sosial-humaniora. Teks sosial-humaniora-seni memiliki kompleksitas yang tinggi dan posisi bahasa-sastra menempati unsur utama. Agak aneh kalau dosen hanya menyalin tanpa “rasa pribadi”.
Plagiarisme bisa disebut sebagai musuh kreativitas. Karya tulis dalam bentuk apapun adalah karya intelektual yang tidak bisa dikanibalisasi seenaknya. Ada otoritas penulis (the author) yang tidak bisa dijagal tanpa etika oleh pembaca (the reader). Pengambilan karya sebelumnya harus menggunakan anotasi/kutipan/bibliografi sebagai wujud penghormatan atas karya seseorang. Bahkan pengambilan karya orang lain ke dalam karya sendiri tidak boleh lebih 20 persen.
Padahal pascareformasi fasilitas penunjang peningkatan kualitas dosen sudah begitu terbuka lebar. Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan angggaran pendidikan mencakup sedikitnya 20 persen dari total anggaran pembangunan.
Fasilitas penelitian bagi dosen sudah cukup terbuka, tapi kualitas dosen tak kunjung meningkat. Anggaran penelitian yang besar itu berbanding terbalik dengan jumlah publikasi. Jangankan publikasi jurnal, publikasi di media massa pun sangat minimal. Bisa disimpulkan penelitian hanya untuk mendukung kesejahteraan finansial, bukan mengemburkan kualitas akademis dan talenta penulisan.
Anti-kreativitas
Mungkin penting melihat kembali analisis provokatif Prof. Ng Aik Kwang dari Queensland University, Why Asians Are Less Creative Than Westerners (2001), menjelaskan kenapa kreativitas tidak cukup hidup di Asia dibandingkan di dunia Barat. Tak perlu mendebat secara verbatim isi buku itu, ini kita bisa jadikan bahan refleksi untuk melihat pengalaman sekitar, termasuk di kampus-kampus Nusantara.
Menurut Prof. Kwang, hal itu bermula dari kelirunya filsafat pendidikan yang dianut. Pendidikan di Asia cenderung ke penghapalan, sedangkan di Barat cenderung ke pemahaman. Para pelajar di Asia cenderung takut kepada kesalahan dan kekalahan, sedangkan di Barat murid-muridnya tidak pernah takut kepada kekeliruan sehingga membuka proses untuk mengeksplorasi hal-hal baru.
Pendidikan di Asia juga cenderung menjejal begitu banyak mata pelajaran, berbeda di Eropa dan Amerika. Proses pendidikan seperti ini akan melahirkan sarjanawan Jack of all trades, but master of none; tahu banyak hal tapi serba tanggung dan tidak mencapai tingkat kepakaran. Salah satu yang terbaik adalah Finlandia yang mempraktikanless is more.
Proses di hulu pendidikan seperti itu pasti melahirkan budaya kematian bagi kreativitas. Kalau angka 6000 dosen yang gagal sertifikasi itu dijadikan bahan refleksi, terlihat bahwa dunia kreatif dan akademis sesungguhnya telah lama menjadi zombie. Budaya di kampus lebih beraroma birokratis, patrimonialis, dan politis. Budaya itu akan melahirkan perilaku negatif lainnya, seperti malas meng-up date pengetahuan, tidak tertarik pada informasi selain bidang pengajaran yang digeluti, dan menjauhi wacana publik.
Jika matinya kreativitas dan lahirnya plagiarisme di kampus-kampus tidak terlihat karena ada kondisi saling melindungi, lain halnya plagiarisme di ruang publik seperti tulisan di media massa dan repository. Kasus seperti ini dengan mudah terlacak. Akan selalu ada mata yang memerhatikan praktik ketidak-jujuran dengan menganibalisasi karya orang lain menjadi karyanya.
Apalagi di dunia digital dan online yang semakin berkecambah, mengunduh karya-karya lain yang tersebar di banyak situs sungguh mudahnya. Seseorang dengan integritas moral rendah akan tergoda mengambil karya orang lain, mengubah-suai secara gramatik beberapa paragraf, selanjutnya mengambil roh tulisan orang lain dan memasukkan ke dalam tubuh tulisan sendiri.
Dengan praktik seperti disebut di atas apakah bisa disebut plagiasi? Di dunia musik, kemiripan 8 bar saja dianggap karya plagiat. Apalagi meniru komposisi atau bagian dari literatur seseorang tanpa menyebut sumber pasti juga plagiarisme.
Secara satir, komedian-penulis-produser Amerika, Steven Alexander Wright menyatakan, “to steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research”. Maksudnya tentu saja dengan membaca banyak karya dan melihat karya-karya yang lain, kita akan terbuka wawasan, energi, dan kreativitas untuk melahirkan karya sendiri serta menjauhkan diri dari keinginan mencuri-curi karya orang lain.
Dalam dunia akademis, tradisi plagiarisme terjadi karena tidak adanya semangat meneliti, membaca, dan mengamati secara tekun dan seksama. Jika pun ada proyek penelitian, hanya rutinitas tanpa makna. Akhirnya, selama budaya malas, korup, dan tidak kreatif masih menjangkiti, selama itu pula plagiarisme menjadi wabah.
Penulis adalah seorang antropolog dan peneliti di Aceh
Editor : Trisno S Sutanto

Diam-diam Ukraina Gunakan Rudal Jarak Jauh dari AS, Serang W...
WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Ukraina untuk pertama kalinya mulai menggunakan rudal balistik jarak ...