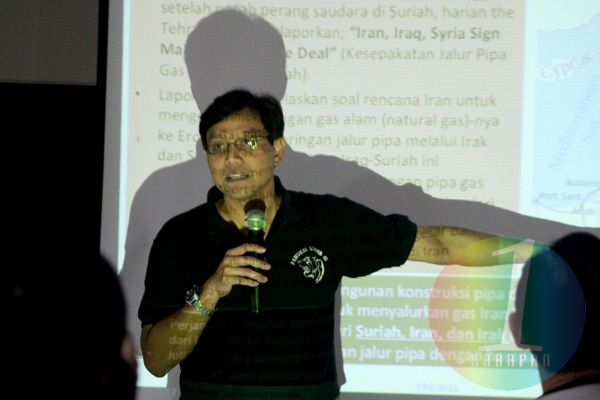Habis Kartini, Terbitlah Suwardi
Lewat pergumulan panjang Ki Hadjar Dewantara merumuskan filsafat pendidikan khas Indonesia yang berlandaskan "ngemong". Apakah masih relevan?

SATUHARAPAN.COM - Kedua tokoh itu, Raden Ayu Kartini dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat hidup pada jaman yang sama. Kartini lahir lebih dulu, 21 April 1879 sementara Suwardi lahir tanggal 2 Mei 1889.
Mereka sama-sama anak bangsawan Jawa: Kartini anak Bupati Jepara, sedangkan Suwardi adalah cucu Pakualam III dari Jogjakarta. Mereka juga sama-sama lulus dari Eropesche Lagere School (ELS = Sekolah Dasar Eropa). Kartini sekolah di Jepara, Suwardi di Jogja.
Namun Kartini terhenti di situ. Ia tidak jadi meneruskan sekolah di Belanda maupun Batavia karena harus kawin, menjadi isteri ke 4 Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Djojoadiningrat. Sementara itu Suwardi – karena lahir sebagai anak laki-laki – diperbolehkan meneruskan pendidikannya. Ia sempat mengenyam pendidikan di STOVIA di Batavia (Jakarta).
Kartini memang tidak bisa meneruskan sekolah, tetapi ia telah menorehkan tinta emas perjuangan bagi kaum perempuan. Sayang, ia meninggal dalam usia muda. Tahun 1904 Ia meninggal dalam usia 25 tahun ketika melahirkan anak. Waktu itu kiprah Suwardi Suryaningrat belum nampak. Suwardi, setelah gagal menyelesaikan pendidikan di Stovia mulai terlibat dalam gerakan kebangsaan Boedi Oetomo (BO) yang lahir tanggal 20 Mei 1908. Ia duduk sebagai seksi propaganda dan melalui BO itulah ia melakukan penyadaran. Ia juga aktif menulis di berbagai media cetak.
Tulisan Suwardi yang terkenal yang kemudian mengubah jalan hidupnya berjudul Als ik een Nederlander was (Seandainya Aku Seorang Belanda) yang dimuat dalam koran De Express tanggal 13 Juli 1913. Koran itu dipimpin oleh Doeuwes Dekker dan Abdoel Moeis. Tulisan itu berupa kritik terhadap Pemerintah Hindia Belanda, yang akan merayakan kemerdekaan Belanda dari Perancis tahun 1913. Untuk perayaan itu Pemerintah mengumpulkan dana termasuk memungut sumbangan dari pribumi. Suwardi sebagai anak bangsa tersinggung atas tindakan pemerintah itu.
Dia menulis: “Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantungnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Berlanda hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikitpun baginya”.
Tulisan itu membuat pemerintah Hindia Belanda tersinggung. Koran De Express dibreidel dan ketiga pengasuhnya: Suwardi, Abdoel Moeis dan Douwes Dekker diadili. Pengadilan memutuskan mereka dihukum dengan cara dibuang ke Belanda. Nah, di pengasingan itulah Suwardi mengalami titik balik. Di Belanda, Suwardi belajar ilmu pendidikan dan memperoleh ijazah Europeesche Akte, ijazah yang sangat bergengsi dan kelak akan mengubah jalan hidupnya menjadi tokoh pendidikan Indonesia. Dialah yang menanamkan asas pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan pribumi. Habis Kartini, Terbitlah Suwardi!
Taman Siswa
Tahun 1919 – sesudah 6 tahun berada di negeri Belanda – Suwardi pulang ke Indonesia. Berpisah jalan dengan kedua teman seperjuangannya, Suwardi bergabung dengan sekolah yang didirikan saudaranya. Pengalaman ikut menangani pendidikan selama 3 tahun itu yang menginspirasi Suwardi mendirikan perguruan nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Dalam perguruan yang didirikan itulah bergabung nama-nama seperti RMP Sosrokartono (kakak kandung RA Kartini, ahli bahasa dan ahli pengobatan spiritual) dan Soekarno (Presiden RI I), Mr. Soenario (yg kelak menjadi Menteri Luar Negeri RI).
Perjumpaannya dengan RMP Sosro Kartono, spiritualis dan pejuang kebudayaan (Jawa) itu memantapkan Suwardi dalam membangun metode pengajaran dan pendidikan yang berbasis kebudayaan melalui Taman Siswa. Sosro Kartono mengajarkan sebuah wejangan hidup yang sangat mendalam: sugih tanpa bandha, digdaya tanpa aji, nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake (kaya tanpa harta, hebat tanpa aji kesaktian, melabrak musuh tanpa prajurit yang menyertai, dan menang tanpa harus mengalahkan).
Dalam usianya yang ke 40 (menurut perhitungan kalender Jawa atau lk. 39 tahun masehi), Suwardi mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara (untuk selanjutnya disebut Ki Hajar). Di perguruan Taman Siswa itu Ki Hajar mengembangkan metode among dalam pengajaran dan pendidikan, yang menempatkan guru sebagai pamong.
Metode among (atau emong), adalah metode yang menekankan tindakan merawat atau memelihara. Siswa didik diibaratkan sebagai tanaman dan guru adalah pemelihara dan perawat. Sebagai orang yang harus merawat dan memelihara, seorang guru dituntut untuk dengan setia menyirami, menyiangi, dan memberi pupuk sehingga tanaman itu tumbuh sehat dan berbuah.
Ini sebuah totalisme, sebuah harmoni atau keselarasan yang menuju pada kesatuan guru dan siswa. Metode itu yang kemudian dia rumuskan menjadi semboyan pendidikan: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani (kala berada di depan memberi teladan, kala bersama-sama atau di tengah-tengah membangun tekad, kemauan dan kehendak yang berarti membangun motivasi, dan ketika berada di belakang memberi dorongan).
Semboyan itu sekali lagi menggambarkan totalisme. Guru dan murid berada dalam satu kehendak yaitu tumbuh dan berkembang. Guru memberikan teladan, memberikan motivasi dan dorongan; dan murid tumbuh dan berkembang dalam arah yang hendak dituju. Sayangnya semboyan itu oleh Departemen Pendidikan hanya diambil bagian belakangnya saja. Dimensi keteladanan dan motivasi serta inspirasi dihilangkan.
Bagi Ki Hajar, pendidikan harus menghasilkan manusia yang cerdas dan berbudi pekerti yang bertolak dari kebudayaan yang luhur. Itulah totalitas manusia: cerdas dan berbudi pekerti luhur. Dari sana kelihatan dimensi sosial dari tujuan pendidikan itu, yaitu bahwa manusia yang berbudi pekerti luhur harus bertanggungjawab pada kelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat.
Pemahaman itu yang kemudian dirumuskan dalam UU No. 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membentuk manusia yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Tujuan pendidikan itu selaras dengan alinea 4 UUD 1945, “…..untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”.
Bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti, itulah pergumulan Ki Hajar dalam meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Sayangnya, di awal orde baru pendidikan budi pekerti itu dihilangkan dan diganti dengan pendidikan agama!
Pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pembentukan karakter manusia dengan dimensi social diganti menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada ketaqwaan kepada Tuhan YME, yang menekankan kesalehan pribadi. Untuk selanjutnya semenjak akhir dasawarsa 1980-an ketaqwaan menjadi tujuan utama dari pendidikan. UU No. 14 tahun 2005 menegaskan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab.
Dalam UU itu kelihatan sangat jelas bahwa tujuan pendidikan yang berorientasi pada pribadi - lepas – pribadi. Tidak nampak dimensi socialnya. Perilaku budi pekerti tidak lagi menjadi bagian dari pembentukan karakter bangsa. Dan karena memang tidak pernah diajar budi pekerti, korupsi atau mencuri dianggap tidak bukan kejahatan asalkan rajin menjalankan perintah agama. Terjadi split of individu, pribadi yang terbelah. Ketakwaan berdiri sendiri berseberangan dengan perilaku keseharian. Berbeda dengan system yang dibangun Ki Hajar: manusia yang utuh yaitu manusia yang cerdas dan berbudi pekerti!
Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2016.
Penulis adalah mantan wartawan
Editor : Trisno S Sutanto

Asuh Cucu Kesepakatan Antara Kakek Nenek dengan Orang Tua
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Program Studi Psikologi Terapan di Fakultas Psikologi Universitas I...