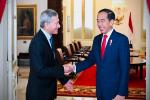Sastra di Hadapan Aksi Terorisme
Sastra melawan globalissi ketakutan
SATUHARAPAN.COM – Terorisme hingga kini terus menjadi ‘momok’ yang menghantui dan menebar kecemasan publik secara mondial sehingga memuncahkan ‘globalisasi ketakutan’. Paras gerakan terorisme bertumbuh dan bermetamorfosa dari mulai jaringan besar hingga dalam wujudnya yang bersifat individual. Bagai ular, terorisme bergerak secara klandestin, dan tiba-tiba beraksi dengan berbagai cara, seperti bom bunuh diri, penembakan, penculikan, dan bentuk kekerasan lainnya.
Indonesia, negeri yang ‘kenyang’ dengan tragedi terorisme. Berbagai aksi terorisme telah menumpahkan bercak-bercak darah di negeri yang elok nan indah ini. Peristiwa penembakan hingga dahsyatnya dentuman bom menjadi senarai contoh dari aksi brutalisme yang telah dipertontonkan oleh kelompok teroris.
Tak pelak, Indonesia tengah berada di tubir ‘darurat terorisme’. Aksi ‘bom besar’ memang tampak mulai reda. Walaupun teror dalam skala kecil dan menengah masih terjadi secara sporadis. Yang pasti, ini bukan berarti cerita tentang terorisme telah usai. Tumbuhnya ‘benih-benih’ terorisme dalam wujud radikalisme terus merekah dan menyemai tunas-tunas yang lambat atau cepat akan membesar. Radikalisme yang menyorongkan intoleransi melalui khobah-khotbah takfiri (pengkafiran) serta tindakan kekerasan terus berlaga memantik kepanikan. Belakangan munculnya ISIS dengan brutalismenya dan mendapat sambutan herois dari beberapa kelompok muslim di negeri kita, membuat situasi kian mencekam..
Terorisme tidak lahir dari ruang hampa. Awalnya, ia bisa berbentuk ‘kepompong’ yang lambat laun bermetamorfosa menjadi wujud utuh. Terorisme muncul dari benih-benih yang terus bertumbuh dalam rupa radikalisme. Radikalisme yang kian menggumpal, akan berpotensi menjasad menjadi terorisme.
Apa yang terpampang dalam aksi terorisme. Tubuh-tubuh terkoyak, jiwa-jiwa meratap disambar bom yang menyalak. Tak ada penyesalan dalam diri teroris, malah berbangga telah menaburkan ‘pesan langit’. Karena ia berlanggam idiologis dan keagamaan sempit yang nyaris sulit dilumerkan. Dengan ini-mengutip Rene Girard-betapa hubungan yang suci dan kekerasan mengungkapkan suatu “hasrat mimetik” manusia.
Saatnya Sastra Mengaum
Sastra melesak dari jiwa-jiwa kepedulian yang bermataair dari kegalauan, keperihan dan kepedihan. Ia menjadi pengembaraan kata-kata yang melampaui realitas baku, kaku, dan segala rupa verbalitas. Kebekuan dicairkan, kenyataan diwartakan, misteri disingkapkan dan energi makna menghablur selaras dengan kedalaman jiwa yang terus bertafakur. Terbitlah pencerahan yang akan terus menyinari cita kedamaian, cinta kasih dan persaudaraan.
Karya-karya sastra yang mengungkap soal terorisme terasa masih langka. Beruntung, ada beberapa karya yang bisa dideretkan seperti novel Damien Dematra yang bertajuk “Demi Allah Aku Jadi Teroris”, dan novel grafis “Kutemukan Makna Jihad”. Ada pula novel terjemahan berjudul “Istriku Teroris”, karya Yasmina Khadra. Yang menarik juga, Khoirul Ghazali, narapidana teroris kasus perampokan bank CIMB Niaga Medan dan pelatihan di Jantho Aceh, sudah menorehkan pertobatannya melalui novel karyanya “Kabut Jihad”.
Belum banyak memang. Walau cukup menempiaskan asa, karena setidaknya telah meruap kesadaran di lingkungan sastrawan. Sisi lain, ini menimbulkan tanya, apakah tema soal terorisme dipandang kurang seksi? Terorisme masih dipandang ranah penindakan oleh Densus 88. Sementara saat ini, sudah kuat kesadaran dari berbagai pihak bahwa yang perlu dikedepankan adalah upaya pencegahan terorisme. Upaya ‘hard power’ perlu diimbangi dengan upaya ‘soft power’.
Selama ini, pergulatan untuk menolak dan melawan terorisme lebih dicungkupkan pada narasi-narasi formalitas melalui patok-patok keagamaan yang rigit serta standar keilmian yang melulu akademis. Sementara ruang-ruang kejiwaan yang mampu menghablurkan kreasi, imaji dan konsepsi untuk melawan kekerasan dan terorisme terasa masih berada di ‘pingitan’.
Di hadapan amuk terorisme, sastra perlu kembali diwedarkan. Paras kecantikan kata-kata perlu kembali di face off. Ia akan makin menukik lebih mendalam, menerobos ruang-ruang kosong yang ditinggalkan atau terlewatkan oleh cara pandang ‘ilmiah’ yang menggunakan parameter yang lebih mengagungkan segala hal yang ‘terstandarisasi’ dan ‘tersertifikasi’.
Sastra mampu menarasikan satu fenomena anomali yang tengah mengancam kehidupan kebangsaan kita saat ini. Dengan kemampuan menjabarkan secara detil dan gamblang, sebuah karya sastra akan mampu memotret secara memukau realitas terorisme berikut kisi-kisinya dan dampak nilainya. Sastra berwatakkan manusiawi, terhindar dari bias politik dan kebencian, berpandukan kearifan dan menyentuh sukma. Maka, karya sastra akan mampu menguarkan pemahaman yang mendalam perihal sisik melik terorisme.
Demikianlah, dengan balutan sastra yang mencacah-cacah emosi, maka penyingkapan sastrawi akan bisa menjadi ‘deteksi dini’ akan adanya kemungkinan pergeseran modus dan pelaku terorisme di tanah air. Sembari itu, sastra mampu meneguhkan kredo, bahwa Islam adalah agama yang berpihak pada kehidupan dan kemanusiaan (din al-hayat), bukan agama kematian (din al-maut) yang memanjakan surga dengan bidadari cantik untuk mengamalkan tindakan teror atas nama kesucian.
Maka tak ayal lagi, sastra niscaya menjadi artikulasi dalam mewujudkan perdamaian dan seiring itu sastra bisa menjadi ‘amunisi’ untuk berperan aktif menanggulangi terorisme. Para sastrawan dipanggil untuk mampu mengembalikan pada suara masyarakatnya yang masih memiliki nilai-nilai laten yang kuat baik berdasarkan agama maupun adat istiadat.
Dengan gelora jihad sastrawan, sastra bisa menjadi artikulasi perdamaian melawan terorisme. Ya, para sastrawan perlu dibangunkan kembali untuk meradikalisasi dan melesakkan ‘ulu batinnya’ demi mengempiskan kegarangan terorisme.
Penulis adalah editor buku “Pengantin Langit, Antologi Puisi Menolak Terorisme”

Diam-diam Ukraina Gunakan Rudal Jarak Jauh dari AS, Serang W...
WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Ukraina untuk pertama kalinya mulai menggunakan rudal balistik jarak ...